Jika semua manusia pada dasarnya baik dan hasrat terdalam mewujudkan kebaikan, mengapa begitu sulit menerima dan mewujudkannya?
uatu hari di tepi pantai, riak-riak air saling berbicara satu sama lain. Salah satu riak kecil berkata, "Oh, betapa hebatnya gelombang besar itu! Ia sangat dahsyat, dapat mengangkat kapal yang paling besar, dapat pula mengempaskannya ke karang. Betapa tak berartinya aku dibandingkan dengannya".
Riak air yang lain menyetujui pandangan riak yang pertama tadi dan mereka semua tertunduk lesu, merasa diri begitu kecil dan tak berarti. Salah satu riak air yang bijaksana berkata, "Saudaraku... engkau keliru.. Engkau tidak berbeda daripadanya... Sesungguhnya, kita (riak kecil) dan dia (gelombang besar) sama saja.. kita adalah air..".
Ketika riak kecil tadi mendengar perkataan temannya, hatinya yang murung seketika menjadi cerah. Ia menyadari bahwa sekalipun kelihatannya begitu berbeda antara dirinya yang hanya riak kecil dan gelombang besar nan dahsyat; sesungguhnya mereka sama: mereka adalah air...
Beberapa waktu yang lalu penulis menerima sepucuk surat dari orang yang tak dikenal. Ternyata yang menulis surat tersebut adalah seorang pasien skizofrenia yang sedang berobat jalan. Sebut saja pasien tersebut bernama Yanto (bukan nama sesungguhnya). Yanto rupanya membaca salah satu buku karya penulis dan terkesan oleh isinya. Ia terdorong untuk menulis surat, memuji buku karya penulis dan kemudian banyak bercerita tentang riwayat hidupnya.
Penulis yang bersimpati pada perjalanan hidup Yanto dan perjuangannya untuk memulihkan diri, membalas surat tersebut sehingga terjadi korespondensi untuk beberapa waktu. Salah satu hal yang menarik perhatian dari surat-surat Yanto adalah: Di dalam surat-suratnya, Yanto selalu merendahkan diri secara berlebihan (self-devaluating) dan menyebut diri orang yang hina dan tak berarti. Sebaliknya ia selalu meninggikan dan memuji (idealizing) penulis.
Di dalam literatur Psikoanalisis, perilaku yang ditunjukkan oleh Yanto merupakan salah satu defense mechanism yang disebut idealization, yaitu upaya mengatasi rasa rendah diri yang ekstrem dengan cara mengidealisasikan orang lain dan memiliki fantasi menyatu dengan/diterima oleh orang tersebut.
Di dalam defense mechanism ini, pasien mendistorsikan pandangan tentang dirinya sendiri berupa devaluasi diri yang ekstrem, dan juga mendistorsikan pandangan tentang orang lain berupa penghargaan yang berlebihan. Pasien yang melakukan ideali- zation akan tergantung secara emosional pada objek idealisasinya.
Bila objek (orang) tersebut menerimanya, ia akan bahagia; namun bila objek tersebut menolaknya, ia akan merasa sangat terpuruk dan terluka. Maka, akan selalu jadi kekhawatiran besar bagi pasien, apakah ia cukup baik untuk diterima dan dikasihi oleh objek idealisasinya ataukah tidak. Keraguan diri yang amat besar akan selalu membuatnya terombang-ambing antara emosi positif dan emosi negatif. Hal ini menjadi sumber penderitaan baginya.
Devaluasi Diri
Cerita di atas adalah contoh ekstrem tentang seseorang yang melakukan devaluasi diri, dan sangat menderita karenanya. Namun, devaluasi diri tidak hanya ditemui pada pasien-pasien dengan gangguan jiwa berat, melainkan dalam berbagai tingkatan sangat mudah dijumpai pada banyak orang, dari berbagai tingkatan sosial-ekonomi dan beragam latar belakang budaya. Sangat mudah bagi kita untuk menemukan kekurangan dalam diri sendiri ataupun dalam diri orang lain; sebaliknya tidak mudah melihat dan mengakui suatu kebaikan dalam diri.
Devaluasi diri adalah salah satu sumber utama penderitaan bagi manusia. Devaluasi diri bukanlah sesuatu yang alami, melainkan merupakan suatu penyimpangan karena bertentangan dengan hasrat dasar yang ada pada semua manusia, yaitu hasrat agar dirinya dipandang baik, diterima, dimengerti, dicintai. Dan tahukah anda? Hasrat tersebut sepenuhnya sah! Semua orang memang berhak dipandang baik, diterima, dimengerti dan dicintai, karena manusia pada dasarnya adalah baik. Pada mulanya semua orang adalah baik, dan tidak ada keinginan lain dalam dirinya selain untuk menjadi baik dan mewujudkan potensi kebaikan yang dimilikinya.
Dapatkah anda menerima itu? Bahwa anda sesungguhnya adalah baik, dan keinginan anda yang terdalam adalah untuk menjadi baik. Kalau anda sungguh percaya bahwa anda diciptakan oleh Yang Maha Baik, maka mestinya anda yakin bahwa anda pasti baik. Dan kalau saja anda sungguh mengerti bahwa anda (sudah selalu) baik, maka secara alami kebaikan dalam diri anda akan bertumbuh, sehingga anda tidak perlu mati-matian berusaha untuk menjadi lebih baik.
Usaha yang (terlalu) keras untuk menjadi lebih baik adalah suatu pengakuan bahwa anda masih menyimpan keraguan dan merasa diri tidak baik. Semakin anda berusaha untuk menjadi lebih baik, bukankah semakin buruk jadinya?
Kalau semua manusia pada dasarnya baik dan hasrat terdalamnya adalah mewujudkan kebaikan, mengapa begitu sulit menerima dan mewujudkannya? Mengapa banyak sekali orang yang dalam perjalanan hidupnya akhirnya menyangkal dan menolak kebaikan dalam diri mereka dan menjadi "buruk?" Abraham Maslow menyebut gejala penolakan akan kebaikan diri itu the Jonah's Syndrome (sindrom Yunus). Kita mengetahui cerita Nabi Yunus, yang memilih lari dari perintah Tuhan untuk melakukan kebaikan. Yunus adalah contoh ekstrem seorang manusia yang enggan dan menolak panggilan Tuhan. Ia bukan satu-satunya Nabi yang melakukan hal tersebut.
Nabi Musa pada mulanya mencoba berkelit dari panggilan Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir karena merasa dirinya tidak pandai bicara. Nabi Yeremia, ketika dipanggil Tuhan juga merasa dirinya tidak pantas dan masih terlalu muda; dan masih banyak contoh lain. Yunus mungkin adalah contoh yang paling ekstrem. Ketika Tuhan mendekatinya, ia lari daripadanya, meskipun sebenarnya hal tersebut adalah absurd.
Seseorang tidak dapat lari dari Tuhan, karena Tuhan senantiasa ada di dalam kita dan kita senantiasa ada di dalamNya. Maka, lari dari Tuhan seperti yang dilakukan Yunus hanyalah ilusi. Yang sebenarnya dilakukannya adalah lari dari dirinya sendiri. Bukan Tuhan yang menolaknya, tapi dirinya sendirilah yang menolak diri.
Kesejatian Diri
Dan apakah sumber penolakan diri tersebut? Tidak lain daripada keabaian/ ketidaksadaran akan kesejatian diri (ignorance of the true self). Sejatinya manusia adalah kudus dan Fitri, putih bersih dan kaya akan cinta Allah. Orang Kristen menyebut bahwa manusia adalah anak Allah yang ditempatkan di Eden (Nirvana). Tidak ada penderitaan di Eden, karena di Eden manusia mengenal identitasnya yang terdalam, yaitu anak Allah.
Para pembaca yang budiman, anda ingat cerita tentang anak yang hilang? Anak bungsu yang meminta warisan dari Bapanya, pergi dan berfoya-foya menikmati segala kesenangan dunia, sampai akhirnya ia jatuh miskin dan menjadi penjaga ternak babi. Anak bungsu itu adalah simbol manusia yang melupakan identitasnya sebagai anak Allah dan memisahkan diri dari Allah.
Tidak ada kemiskinan yang lebih parah daripada kehilangan identitas diri. Dan saat si anak bungsu melupakan identitasnya yang sejati, ia menjadi yang termiskin di dunia, padahal sebenarnya ia kaya raya. Saat itu ia berpindah dari Surga ke Neraka. Neraka bukanlah suatu tempat penyiksaan yang nanti akan ditempati orang berdosa setelah mati. Neraka adalah kondisi penderitaan yang terdalam karena abai/tak sadar/lupa akan identitas sejati.

Remembrance
Maka solusi untuk mengatasi akar penderitaan manusia adalah dengan penyadaran untuk mengingat kembali identitasnya yang sejati. Ken Wilber, seorang tokoh Integral Psychology, menyebut proses penyadaran ini dengan istilah remembrance, yaitu mengingat kembali.
Yang dimaksudkannya adalah: Nirvana, Eden, pencerahan, transendensi atau apapun istilahnya, bukanlah sesuatu yang semula tiada yang kemudian ditambahkan pada diri kita, Ia sudah selalu ada sejak semula!
Pada mulanya manusia tidak miskin papa akan segala sesuatu yang paling dibutuhkannya untuk mengalami kebahagiaan sejati; sebaliknya, pada mulanya manusia sudah kaya raya dan memiliki utuh kebahagiaan sejati tersebut.
Maka Ken Wilber mengatakan proses transendensi adalah proses remembrance. Seperti anak bungsu di dalam cerita, yang di puncak penderitaannya ingat kembali pada rumah Bapanya, pada siapa dirinya sesungguhnya dan mulai berjalan pulang, maka proses "penyembuhan" akan penderitaan jiwa kita yang terdalam adalah proses penyadaran untuk mengingat kembali siapa diri kita yang sesungguhnya.
Dan saat kita memandang kembali pantulan diri kita dalam tatapan penuh kasih sang Bapa, kita akan tertegun menatap kembali wajah kita yang sesungguhnya, wajah yang sudah selalu ada sebelum segala penderitaan hidup ini dimulai. Wajah anak yang terkasih.
Iman Setiadi Arif, Dekan Fakultas Psikologi Ukrida

.jpg)
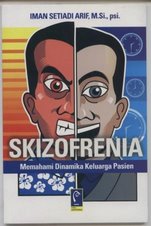
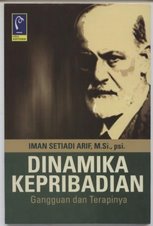



Tidak ada komentar:
Posting Komentar