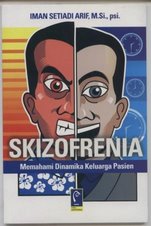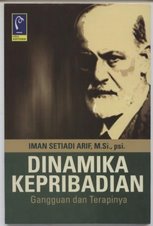Nyalakanlah daku...
Hari-hari ini, masyarakat Indonesia tidak hanya dihebohkan oleh berita gempa di Padang, pemberantasan terorisme di Ciputat atau pemilihan menteri-menteri di kabinet SBY yang akan segera dilantik. Suatu berita "kecil" tapi menohok, juga sedang hangat dibicarakan orang. Yang saya maksud tidak lain daripada rencana kedatangan Maria Ozawa – alias Miyabi, seorang aktris film porno Jepang ke Indonesia. Kedatangan Miyabi dalam suatu rencana dagang pragmatis, untuk main di film produksi Indonesia ternyata mengundang kontroversi yang sangat besar. Produser film yang mengundang Miyabi tentunya tidak mengundangnya karena talenta acting yang menonjol, namun dikarenakan daya jualnya yang tidak diragukan. Saya khawatir bahwa apapun hasil akhir dari kontroversi ini, pihak-pihak yang saling bertentangan dalam kontroversi ini tanpa sadar telah menguntungkan dan mempromosikan film Miyabi tersebut.
Salah satu aspek kehidupan yang selalu menimbulkan kontroversi dari jaman ke jaman, adalah kehidupan seksual. Tidak hanya bagi kita, orang Timur – meskipun sekarang dikotomi Barat/Timur tak sekaku dulu lagi – namun juga bagi orang Barat yang – katanya – jauh lebih liberal dan "tercerahkan". Bahkan di jaman ultra modern seperti hari ini, sebagian besar orang masih merasakan pertentangan dalam diri ketika bersikap tentang area kehidupan yang satu ini.
Di satu sisi, kalau kita mau mengakui, seks selalu merupakan salah satu obsesi kita. Kapan terakhir kali anda menata penampilan anda – atau bahkan berjuang menguruskan, mengencangkan atau memperbesar otot-otot badan – agar menarik dipandang oleh lawan jenis? Itu adalah isu seksual. Pernahkah anda – mungkin secara diam-diam – membandingkan diri anda dengan orang-orang yang dalam anggapan anda memiliki "performance" seksual mengesankan? Bukankan sampai beberapa waktu yang lalu almh. Mak Erot adalah salah seorang "therapist" yang paling phenomenal, yang bagi sebagian pria dianggap "penyelamat"? Berapa banyak perempuan yang iri dan merindukan untuk punya bibir seperti Angelina Jollie atau bokong seperti Jennifer Lopez? Disadari atau tidak, obsesi kita tentang seks sangat mendarah daging. Dan seperti kita lihat pada contoh-contoh di atas, seks terkait erat dengan rasa keberhargaan diri kita. Bila kita sedang down dan merasa terpuruk, serta meragukan diri sendiri, proyeksinya seringkali berupa semakin meningkatnya obsesi seksual ini.
Di sisi lain seks adalah salah satu topik yang paling dirasakan mengancam. Kita tidak nyaman bicara tentang seks. Ketidaknyamanan yang dengan mudah disamarkan berupa lelucon-lelucon seks yang "garing", atau bualan tentang seks yang mengesankan kepercayaan diri dan menyembunyikan adanya kegelisahan. Kita merasa berdosa karena terus menerus berpikir tentang seks, sehingga mendorong kita untuk bereaksi defensif dan bersikap ultra konservatif.
Mengapa kita begitu konflik dan gagap ketika kita berpikir, merasa dan berperilaku seksual? Hal ini merupakan bukti bahwa seks adalah perkara penting dalam hidup kita, meskipun begitu sering disalahpahami. Seks bukan hanya membantu kita untuk beroleh keturunan, tetapi menyangkut fondasi dasar rasa keberhargaan dan keberadaan diri kita. Kita coba telaah mengenai hal ini lebih lanjut.
Pertama-tama, seks bukan sekedar perilaku untuk memperoleh kesenangan, tetapi lebih daripada itu, seks adalah mengenai passion atau gairah hidup itu sendiri. Pandangan yang pernah dikemukakan oleh Sigmund Freud lebih dari 100 tahun yang lalu ini, ternyata didukung oleh temuan-temuan terbaru Neuroscience modern. Seksualitas berkaitan sangat erat dengan emosi manusia; dan emosi ternyata memiliki fungsi dasar bagi keberadaan manusia. Seorang neuroscientist terkemuka yang bernama Antonio Damasio, dari the Brain and Creativity Institute, University of Southern California mengemukakan bahwa emosi adalah elemen kunci yang memungkinkan manusia memiliki kesadaran, sense of self dan kehendak bebas – tidak seperti mesin atau supercomputer secanggih apapun yang tidak akan pernah memiliki kehendaknya sendiri dan pilihan-pilihannya sendiri. Tahukah anda bahwa para ilmuwan telah lama bermimpi untuk dapat menciptakan mesin, komputer dan robot yang memiliki artificial intelligence, dan lebih dari itu, sadar serta memiliki kehendak sendiri. Hambatan mereka untuk dapat melakukan itu bukan dalam hal penciptaan kecerdasan buatan – karena kita tahu bahwa mereka telah berhasil menciptakan supercomputer yang dapat mengalahkan grandmaster catur terbaik dunia. Hambatan mereka tidak lain terletak pada ketidakmampuan untuk menciptakan mesin yang dapat merasa, alias yang memiliki emosi.
Menurut neuroscientist Jaak Panksepp dari university of Washington, ada empat sistem emosi dasar yang berpusat di area Periaqueductal gray (PAG), di pusat otak kita. Keempatnya adalah the seeking system, the rage system, the fear system, dan the panic system. Keempat sistem ini relevan dengan pembicaraan kita tentang seksualitas, khususnya the seeking system (di area ventral tegmental). Sistem ini merupakan mekanisme biologis yang mengatur munculnya selera kita untuk mencari pemenuhan berbagai kebutuhan kita, seperti makanan, perlindungan, dan seks. Secara sederhana, katakanlah ini merupakan motor penggerak atau api gairah kehidupan individu untuk melanjutkan kehidupannya. Seseorang yang mengalami kerusakan di area otak ini, tidak akan memiliki semangat untuk melakukan dan mencari apapun, sekalipun hidupnya terancam, karena kelaparan atau kehausan. Sebaliknya, seseorang yang mengalami hiperaktivitas di area ini, akan menunjukkan perilaku yang lustful, tamak akan makanan, kenikmatan dan seks. Kontrol akan aktivitas area ini terletak di area prefrontal cortex (namun diskusi tentang ini harus ditunda di lain kesempatan karena keterbatasan ruang).
Temuan neuroscience modern ini memberi pencerahan akan peranan seksualitas, emosi dan gairah kehidupan. Seksualitas (passion) dan emosi dapat diibaratkan api yang menyalakan, memberi energi sekaligus ekspresi hidup itu sendiri. Tiada kehidupan tanpa api yang menyalakannya, meskipun tentu saja api yang dibiarkan menyala tanpa kontrol akan menghanguskan hidup itu sendiri. Antonio Damasio menyadari benar hal itu, sehingga fokus penelitiannya sekarang di the Brain and Creativity Institute adalah untuk menyingkapkan peranan emosi dan passion tersebut bagi dimungkinkannya kemunculan kreativitas dan penciptaan karya seni. Damasio bekerja dengan sebagian artist terbaik dunia, meneliti proses kreatif mereka dan mekanisme neurologis yang mendasarinya. Passion, seksualitas, emosi dan tentu saja kontrol atasnya, merupakan elemen-elemen dasar terciptanya karya-karya terbaik manusia dan pengaktualisasian potensi-potensi besar manusia. Tidak heran bila seksualitas memiliki kaitan erat dengan rasa keberhargaan dan kepercayaan diri manusia.
Bagi kita, dapatlah ditarik pelajaran untuk menjaga dan menggunakan api gairah kehidupan itu dengan bijaksana. Bukan dengan menekannya sedemikian rupa sehingga hilang pula semangat dan daya cipta yang dikandungnya, bukan pula dengan mengumbarnya dan merendahkan martabatnya sehingga memerosotkan kemanusiaan kita setara dengan hewan. Melainkan dengan menjadikannya sumber daya cipta yang subur, menyalakannya sebagai pembakar semangat dan memuliakannya dengan karya dan pencapaian kesadaran yang lebih tinggi tentang hakikat kemanusiaan kita. Tulisan ini diakhiri dengan kutipan dari The Doors: Come on baby light my fire..
Iman Setiadi Arif
Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Kristen Krida Wacana (UKRIDA)
Jakarta

.jpg)