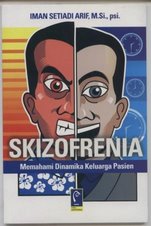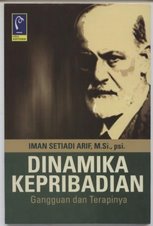Sehari sebelum pilpres di Indonesia, atau sekitar tengah malam menjelang detik-detik pencontrengan di seluruh Nusantara, seorang maha bintang – bahkan seorang raja – memperoleh penghormatan terakhir dari seluruh kerabat dan sahabatnya. Setelah menjalani kehidupan yang sedemikian extraordinary – dengan berbagai kemenangan dan kekalahan, kegemilangan dan kekelaman – ia beroleh istirahat abadi di pelukan Bunda Bumi; mengembalikan cahaya yang selama ini ditebarkannya ke seantero penjuru dunia kepada Sang Maha Cahaya, yaitu yang empunya dan pencipta dirinya. Kematian Jacko tidak menghentikan kontroversi yang seolah terpatri pada jalan hidupnya; sebaliknya hingga hari-hari ke depan tampaknya kita masih akan mendengar kelanjutan kisah misteri seputar kematian, pemakaman dan perebutan (!) warisan dan hak asuh anak-anaknya.
Hidup Jacko sendiri mungkin merupakan salah satu contoh sempurna untuk menggambarkan eksistensi manusia yang rapuh, dalam pergulatan untuk memberi makna pada sekecap kehidupan yang dijalani, menorehkan warna – sekaligus noda – di wajah yang fana. Dilahirkan sebagai anak ketujuh dari sembilan bersaudara the Jackson, Jacko adalah yang terkaya beroleh talenta. Sang ayah – Joe, dan sang ibu – Katherine, tentunya tidak pernah bermimpi bahwa salah seorang anak mereka akan menjadi maha bintang, bahkan disebut the greatest entertainer ever lived oleh khalayak. Menyadari bakat musik anak-anaknya sejak dini, Joe tak ragu-ragu menerapkan disiplin besi pada mereka, tak terkecuali Michael. Banyak kisah yang beredar tentang cara-cara Joe mendidik dan mendisiplinkan anak-anaknya untuk mencapai kesempurnaan dalam menjadi entertainer. Mulai dari tamparan, pukulan, sabetan gesper ikat pinggang, hingga terror mental di malam hari. Bahkan sebagian kisah – yang tak dapat dibuktikan – mengatakan bahwa Joe melakukan sexual abuse pada anak-anak perempuannya. Dalam wawancaranya dengan Oprah Winfrey pada tahun 1993, Jacko sendiri mengatakan bahwa ia seringkali bermimpi buruk tentang kekerasan yang dialaminya di masa kecil. Saat anak-anak lain bermain dengan puasnya, anak-anak the Jackson harus berlatih keras tiap hari; dan mereka jadi bahan tertawaan anak-anak lain. Seringkali Jacko menangis karena kesepian yang menusuk; dan melihat bayangan ayahnya saja kadang membuatnya muntah karena ketakutan yang sangat. Namun Jacko pun mengakui bahwa kerasnya disiplin sang ayah memiliki peranan pada kesuksesan yang diraihnya di kemudian hari.
Masa kecil Jacko dan khususnya perilaku sang ayah bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi pedang itu menancapkan luka yang amat dalam di relung batin Jacko – luka yang tak pernah sembuh seumur hidupnya dan menjadi akar bagi berbagai masalah emosional dan perilaku Jacko yang ganjil; namun di sisi lain pendidikan yang (terlalu) keras tersebut membantu Jacko menemukan sumber kebahagiaan satu-satunya dalam kehidupannya dan jalan pembebasan baginya, yaitu pengaktualisasian talenta musiknya.
Dengan akar luka batin tersebut dalam diri Jacko telah tertanam suatu kecemasan mendasar (basic anxiety) dan suatu cedera pada rasa keberhargaan dirinya (narcissistic injury), yang akan menghantui seumur hidupnya. Bilamana seseorang dilukai oleh seseorang yang sangat bermakna bagi dirinya (selfobject1) maka sang aggressor akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam diri, sehingga selama ia hidup dan ke mana pun ia pergi, ia akan selalu membawa sang aggressor dalam dirinya. Trauma sesungguhnya tidak hanya dialami satu kali ketika peristiwa traumatik itu terjadi, tetapi di level ketidaksadaran akan diulang-ulang terus menerus. Hal ini akan menggerus keutuhan ego atau karakter yang bersangkutan.
Ego yang telah mengalami cedera mengalami pelemahan, perpecahan dan keterasingan. Beberapa gejala yang dapat kita saksikan sebagai konfirmasi akan hal tersebut antara lain adalah bagaimana Jacko selalu tercekam kesepian yang mendalam dan keterasingan baik dengan orang lain maupun dengan dirinya sendiri. Sebagai seorang yang menyimpan luka, ada sensitivitas yang berlebih dalam dirinya. Ia tidak pernah merasa nyaman ketika bersama orang lain – terlebih dalam konteks relasi intim. Hal ini diperburuk oleh perlakuan orang lain kepadanya, yang tak dapat melihat diri Jacko yang sejati, yang masih berupa kanak-kanak yang terluka, melainkan lebih senang memandang topeng Jacko, yaitu Jacko sang Mega Bintang. Kita tahu bahwa Jacko memiliki relasi intim dengan beberapa wanita tercantik di dunia. Sebut saja Tatum O’Neal yang merupakan cinta pertamanya, Brooke Shields – bintang tercantik era 80’an; bahkan Jacko pernah menikah dua kali; pertama dengan Lisa Marie Presley dan kedua dengan Debby Rowe yang memberinya seorang putera dan seorang puteri. Namun dalam semua relasi tersebut, Jacko tak pernah sungguh-sungguh merasa nyaman dan dapat menjadi dirinya sendiri, bahkan mengalami kesulitan untuk menjadi intim secara seksual. Menurut kata-kata Jacko sendiri, satu-satunya tempat di mana ia sepenuhnya merasa nyaman adalah bilamana ia berada di panggung, menghipnotis para pemujanya dengan tarian dan nyanyiannya. Di dunia panggung yang maya, Jacko merasa bahagia dan bebas, sementara di dunia nyata ia sangat menderita, kesepian, ketakutan dan merasa terbelenggu.
Dampak lain dari cedera batin Jacko adalah keterpakuannya secara emosional pada masa kanak-kanak. Dalam dunia psikologi hal ini dikenal dengan istilah fiksasi atau arrested development. Jacko bagaikan Peter Pan yang menolak untuk tumbuh dewasa dan meninggalkan dunia fantasi kanak-kanak menuju realitas dunia orang dewasa dengan segala tanggung jawab dan permasalahannya. Jacko ingin tinggal di fantasi kanak-kanaknya. Dengan kemampuan finansialnya yang seolah tanpa batas, Jacko mewujudkan fantasi tersebut dengan membangun Neverland – dunia di mana anak-anak menikmati masa kanak-kanak abadi, dan segala kesenangan kanak-kanak yang dapat dibayangkan tersedia. Keterpakuan pada masa kanak-kanak dan gejala ketidakmatangan ini oleh Dan Kiley disebut sebagai the Peter Pan syndrome. Kita pun kelak mengetahui bahwa keterpakuan dan kecintaan Jacko pada kanak-kanak, adalah tumit Achilles atau kerentanan yang akan menggusur kejayaannya, dengan munculnya berbagai tuduhan pelecehan seksual pada kanak-kanak yang ditujukan padanya.
Menurut Carl Gustav Jung – seorang pakar tentang ketidaksadaran yang tak kalah mumpuni daripada Sigmund Freud – sesungguhnya keterpakuan pada masa kanak-kanak seperti yang dialami Jacko, memiliki dua sisi – positif dan negatif; bukan hanya menjadi akar bagi berbagai ketidakmatangan dan gangguan emosional seperti misalnya kecenderungan pedophile (ketertarikan seksual pada kanak-kanak) yang dituduhkan kepada Jacko; namun juga memiliki sisi positif karena merupakan pertanda bekerjanya suatu Archetype2 yang disebut Puer Aeternus, yang terjemahannya berarti bocah abadi. Puer Aeternus – yang merupakan inspirasi bagi tokoh Peter Pan – merupakan dewa kanak-kanak yang tak pernah menjadi tua, yang sekalipun mati akan dilahirkan kembali; yang mana merupakan symbol potensi dan kerinduan terdalam manusia akan kekekalan dan kelahiran kembali. Jung mengatakan bahwa Puer Aeternus menyimbolkan perkembangan psikologi paripurna dalam diri manusia. Bila di masa kini manusia hidup dalam batasan egonya yang sempit, maka Puer Aeternus merupakan pertanda transendensi di mana bila manusia mau mencapai pencerahan, meraih pembebasan dari penderitaan (mokhsa) maka ia harus dilahirkan kembali dan menjadi seperti anak kecil. Jung bahkan mengatakan bahwa kata-kata Yesus yang berbunyi,”Sesungguhnya barangsiapa tidak menyambut Kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya", merupakan salah satu ajaran yang senada dengan falsafah Puer Aeternus ini.
Archetype Puer Aeternus yang kuat dalam diri Jacko, menandakan adanya suatu potensi dalam dirinya akan pembaharuan, pertumbuhan dan harapan akan masa depan. Memang Jacko selalu rindu akan dunia yang lebih baik daripada dunia yang dikenalnya saat ini. Ia selalu rindu untuk menyembuhkan dunia – khususnya dunia batinnya sendiri. Ia rindu untuk masuk ke dalam Neverland abadi, bukan Neverland fana yang diciptakannya sendiri. Kerinduan ini membuatnya selalu mencari pembaharuan dalam musiknya, dalam seninya, dalam dirinya. Seperti Puer Aeternus yang selalu dilahirkan kembali, ia selalu bangkit saat badai menderanya; ia selalu menciptakan kembali dirinya sendiri, melalui musik yang menghibur dunia dari dekade ke dekade. Kalau ada orang yang mengubah penderitaan dan trauma masa lalu menjadi sumber kreativitas yang tiada habisnya, Jacko-lah orangnya. Menjelang wafatnya, Jacko sedang menyiapkan suatu karya terakhir yang akan menjadi warisannya bagi dunia seni popular, yang akan diwujudkan berupa konser terakhir di London, ketika sang takdir menjemputnya.
Jacko belum mencapai pembebasan itu. Ia masih terluka dan masih merasa dirinya terbelenggu dan didera oleh berbagai derita, baik fisik, emosional dan sorotan publik yang kejam. Kerinduan, kehausan dan kegelisahan yang tanpa henti mendera dirinya tidak dapat dipenuhinya di dunia ini. Namun saya percaya, bahwa Jacko mati bahagia, karena ia mati ketika sedang mencipta maha karya, ia mati saat hendak memberikan sehabis-habisnya yang terbaik dalam dirinya, bagi dunia. Dan saya percaya bahwa pada akhirnya pembebasan itu tiba, penantian itu berakhir, Puer Aeternus telah mengantarnya ke Neverland baka; dan sang Peter Pan yang terluka itu akhirnya disembuhkan dan terbang kembali ke rumahnya yang sejati. Selamat jalan Jacko, terima kasih atas perjuanganmu menyembuhkan dunia. Dunia telah menjadi lebih baik karenamu.
1 Tulisan “selfobject” memang sengaja tidak dipisah, tanpa spasi. Hal ini untuk menunjukkan bahwa antara self (diri) dengan orang lain yang sangat berarti bagi diri (object), telah menjadi suatu kesatuan. Object telah menjadi bagian dari diri, sehingga tiada lagi diri tanpa object. Bilamana suatu peristiwa memisahkan object dan diri tersebut, maka sang diri akan merasa seolah dirinya diamputasi sehingga kehilangan itu akan meninggalkan rongga yang besar dalam sang diri.
2 Dalam bahasa sederhana, archetype dapat diartikan sebagai makna dasar dan potensi dalam jiwa yang bersumber dari pengalaman umat manusia selama berabad-abad.

.jpg)