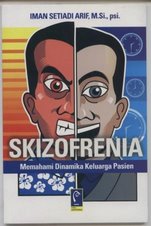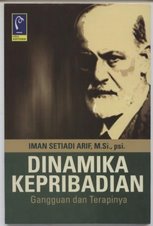Melampaui Batasan Keberadaan
Tulisan ini pernah dimuat di Harian Suara Pembaruan
Miyamoto Musashi adalah seorang legenda Samurai yang hidup di era Tokugawa (antara tahun 1603 – 1867) di Jepang. Pada masanya, ia adalah pendekar yang tak terkalahkan. Ia berkeliling negeri, menantang dan mengalahkan perguruan-perguruan Samurai paling ternama, seperti Yoshioka dan Yagyu dan terakhir ia mengalahkan Sasaki Kojiro - seorang pendekar terhebat (dan terganas) di masa itu - dengan hanya menggunakan pedang kayu yang dirautnya sebelum pertempuran dimulai. Setelah itu ia tidak pernah bertempur lagi, sekalipun banyak pendekar muda bermunculan dengan ambisi untuk mengalahkannya. Di masa tuanya ia lebih terkenal sebagai ahli kaligrafi, tembikar, upacara minum teh dan pelukis. Ia menulis buku yang berjudul “Buku tentang lima cincin”, yang sekarang banyak menjadi sumber inspirasi bagi para manager dalam mengelola bisnis di tengah persaingan yang ketat.
Musashi berasal dari keluarga Samurai miskin. Ayahnya otoriter dan keras luar biasa, sehingga ibu Musashi tidak tahan dan meninggalkannya beserta kedua anaknya yang masih kecil. Musashi tumbuh menjadi pemuda berandalan, sampah masyarakat yang ditakuti dan dibenci warga kampungnya. Sampai suatu ketika ia bertemu dengan seorang guru Zen bernama Takuan Soho yang membangkitkan pencerahan dalam dirinya. Dalam pencerahan itu ia menyadari bahwa hidup adalah batu permata yang masih harus digosok dari waktu ke waktu hingga sinar cemerlangnya muncul. Seorang Samurai menimang-nimang permata tersebut dengan penuh kasih sayang sampai tiba saatnya untuk menyerahkannya dengan penuh kehormatan dalam menjalankan kewajiban. Sejak perjumpaan dengan Takuan, dimulailah petualangannya mencari kesejatian melalui jalan pedang.
Setelah mengalahkan lawan-lawan paling berat dan berulangkali selamat setelah berhadapan muka dengan muka dengan maut, Musashi tidak merasakan kepuasan sejati. Tidak ada lagi yang bisa diraih dan ia merasa menghadapi jalan buntu. Dalam keputusasaannya ia (kembali) berjumpa dengan seorang guru Zen yang bernama Gudo, yang membuka mata hatinya sehingga ia mencapai pencerahan kedua yang membawanya pada kesempurnaan. Pendakian kesempurnaan yang dilalui Musashi dapat digambarkan melalui tiga tahap. Di tahap pertama pedang dan pendekar menyatu sehingga dengan menggunakan ranting, bambu atau bahkan selembar daun saja si pendekar dapat membunuh lawannya. Di tahap kedua: pedang tidak lagi memiliki wujud, melainkan ada di hati si pendekar, sehingga dari jarak 100 mil pun ia dapat membunuh lawannya. Di tahap tertinggi, tidak ada pedang – tidak ada pendekar, tidak ada lagi keinginan untuk membunuh, sang Pendekar (dengan “P”) merangkul segalanya dan hanya kedamaian yang tersisa.
Perjuangan Ego mencapai Superioritas
Cerita di atas adalah metaphor yang baik sekali untuk menggambarkan perkembangan kepribadian manusia. Seorang psikoanalis bernama Alfred Adler (1930) berteori tentang perjuangan Ego untuk melakukan kompensasi atas inferioritasnya menuju keadaan Superior. Dalam proses kompensasi itu seseorang mula-mula menjadi agresif, kemudian beralih menjadi ingin menguasai orang-orang lain dan kemudian berjuang mencapai keadaan unggul (state of excellence/superior). Seperti Musashi yang dari hari ke hari menempa keterampilannya berpedang, manusia terus meningkatkan kekuatan Ego nya dalam pergumulan hidup sehari-hari.
Kepribadian yang sehat membutuhkan Ego yang kuat. Ego yang kuat merupakan suatu pencapaian yang luar biasa, sebagai hasil pergumulan dalam kehidupan. Erik H. Erikson (1950, 1968) dengan teori perkembangan psikososialnya telah menerangkan bagaimana Ego berkembang mencapai kematangan, setelah melewati berbagai krisis sejak masa kanak-kanak sampai di usia lanjut.
Ego yang kuat ditandai oleh kesediaan untuk menunda kesenangan dan suatu kegairahan untuk meningkatkan efektivitasnya terus menerus dalam berinteraksi dengan lingkungan. Seperti Musashi muda yang haus kemenangan, Ego yang kuat selalu beralih dari satu prestasi ke prestasi lain, mencari tantangan baru yang lebih sulit untuk ditaklukkan.
Puncak pencapaian Ego adalah yang disebut oleh Abraham Maslow sebagai aktualisasi diri. Dalam kondisi aktualisasi diri, seseorang telah memaksimalkan realisasi potensi-potensi dirinya. Segenap bakat dan kemungkinannya untuk berprestasi telah diwujudkan sehingga seseorang telah mencapai kondisi Superior. Apakah hal ini menimbulkan kepuasan yang sejati? Seperti contoh dalam cerita Musashi di atas, jawabannya adalah tidak. Kondisi di mana seseorang berada di puncak superioritas, seringkali menimbulkan konflik yang lebih besar dan membuatnya terisolasi dari orang-orang lain. Dari penjara Inferioritas, ia masuk ke penjara Superioritas.
Transendensi untuk melampaui keterbatasan Ego
Untuk mencapai pembebasan sejati, Ego yang sempit harus dilampaui. Ken Wilber (1996) mengatakan dengan ringkas dan padat: Perkembangan adalah Evolusi; Evolusi adalah Transendensi; dan Transendensi menuju pada tujuan akhir yaitu Atman, atau kebersatuan kesadaran di dalam Tuhan. Di dalam kondisi Atman inilah seseorang dapat melampaui kekerdilan dan kedangkalannya menuju keluasan dan kedalaman. Dalam kondisi inilah damai diperoleh.
Sebelum seseorang mencapai realisasi diri final berupa Atman, kepribadian berada di bawah rezim Ego. Keberadaan di bawah rezim Ego adalah keberadaan yang dangkal, sempit dan penuh keterpecahan. Erich Fromm (1947, 1955, 1964) melukiskan kondisi dasar manusia yang penuh kontradiksi di bawah rezim Ego. Manusia memiliki ciri-ciri kebinatangan, tapi ia bukan binatang. Manusia merupakan bagian dari alam, tapi ia juga terpisah dari alam. Manusia rindu untuk mengalami kebersamaan dan persaudaraan sejati dengan orang lain, tapi ia tak hentinya membenci dan menghancurkan sesamanya. Bahkan di dalam dirinya sendiripun manusia penuh keterpecahan. Bagian dirinya yang satu membenci dan menolak bagian dirinya yang lain, dan manusia selalu menemukan dirinya melakukan sesuatu yang tidak dikehendakinya atau tidak melakukan apa yang sesungguhnya dikehendakinya, sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus. Keterpecahan ini menimbulkan keterasingan dan kesepian mendalam yang menurut Erich Fromm merupakan akar segala perilaku menyimpang dan destruktif manusia.
Puasa dan Matiraga untuk “Mematikan” Ego, membangkitkan Atman
Untuk melampaui keterbatasan Ego, seseorang mesti “mematikan” Ego. Mungkin kita boleh mengutip kata-kata Yesus yang mengatakan bahwa jika biji tidak mati, maka ia tetap tinggal biji; namun jika ia musnah, maka berbuah berlimpah-limpah.
Di dalam setiap agama dan aliran kepercayaan, terdapat berbagai ritus matiraga yang sakral untuk “mematikan” Ego dan mencapai keadaan Moksha (Pembebasan/Pencerahan). Salah satu ritus universal adalah dengan berpuasa. Saat seseorang berpuasa – agama apapun yang dianutnya – ia “mematikan” kedagingannya untuk memperoleh kebangkitan rohani.
Beth Hedva (2001), seorang psikolog transpersonal, mengatakan bahwa proses “mematikan” Ego tidak satu kali jalan, melainkan dilakukan berulangkali melalui siklus kematian simbolik-kelahiran kembali. Jalan universal yang harus ditempuh seseorang menuju pembebasan adalah melalui lima tahap yang harus dilalui berulang kali.
Tahap pertama: Perpisahan (Separation) dari segala hal yang mengikat kita pada keduniawian dan kedagingan kita. Tahap kedua: Pemurnian (Purification) dari segala kemelekatan yang menimbulkan konflik dan penderitaan. Tahap ketiga: Kematian simbolik (Symbolic death) di mana cangkang Ego kita yang sempit dihancurkan. Tahap Keempat: Pencerahan (New Knowledge), di mana kita memperoleh perspektif baru dalam memandang diri, dunia dan orang lain. Kelima: Kelahiran kembali (Rebirth) di mana seluruh diri diperbaharui, dari kekerdilan menjadi keluasan, dari kedangkalan menjadi kedalaman, dari konflik menjadi damai. Dan selanjutnya siklus ini dimulai kembali sampai kita mencapai tujuan final berupa Atman.
Miyamoto Musashi telah menempuh jalan jalan pedang untuk mencari kesejatian diri dan pembebasan. Di akhir perjalanannya, pedang lenyap dan diri (Ego) juga lenyap. Kita pun mesti menempuh jalan kita masing-masing, yang sekalipun kelihatannya berbeda-beda, namun sebenarnya universal, yaitu jalan menuju Pembebasan. Bulan Ramadhan yang baik ini tidak hanya anugerah bagi kaum Muslim, melainkan mengingatkan semua orang yang rindu pada Pembebasan, untuk menempuh jalannya, matiraga dan melampaui kungkungan keberadaannya. Selamat Berpuasa…
Iman Setiadi Arif
Dekan dan staff pengajar Fakultas Psikologi Universitas Kristen Krida Wacana – Jakarta
Kamis, 28 Juni 2007
Mengapa Tuhan Membiarkan Adanya Penderitaan
Mengapa Tuhan MEMBIARKAN adanya penderitaan?
Tulisan ini pernah dimuat di Harian Suara Pembaruan
Bila kita membaca koran setiap harinya, satu yang tak akan lepas adalah membaca tentang berbagai wajah penderitaan di muka bumi. Puluhan ribu orang yang mati di Irak, ratusan ribu nyawa melayang karena Tsunami di Aceh, kekerasan di Poso, korban banjir di Jabodetabek, kriminalitas sehari-hari, dan berbagai penderitaan lain yang dialami secara solitaire tanpa diketahui orang banyak. Penderitaan kerap singgah dalam hidup setiap manusia, dan ketika penderitaan menghampiri hidupnya, orang pun bertanya,”Mengapa Tuhan membiarkan adanya penderitaan?”
Pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2007 ini, umat Kristiani memasuki hari Rabu Abu, yaitu dimulainya masa pantang dan puasa selama 40 hari untuk memperingati sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Puncak dari perayaan ini adalah pada hari tri hari suci, yaitu Kamis Putih, Jum’at Agung dan hari raya Paskah, yaitu perayaan kebangkitan Yesus Kristus dari alam maut. Di masa pantang dan puasa ini, umat Kristiani diajak untuk merenungkan misteri terbesar dalam kehidupan, yaitu bahwa hidup manusia di dunia niscaya adalah jalan penderitaan (via dolorosa) menuju kematian.
Dialektika keberadaan vs. ketiadaan
Pernyataan bahwa hidup adalah suatu perjalanan penuh derita menuju kematian, tampaknya sangat suram dan menyesakkan; tetapi hal itu adalah kebenaran mutlak yang tak dapat disangkal. Tiada kebenaran lain yang lebih mengguncang kenyamanan semu hidup manusia daripada penderitaan dan kematian. Dalam riwayat hidup Siddhartha Gautama, perjumpaannya dengan penderitaan dan kematianlah yang mengguncangkan dunia kesadarannya yang semu dan membuatnya menempuh perjalanan panjang menuju pembebasan, menjadi sang Buddha.
Pada umumnya manusia berusaha menyangkal kenyataan telanjang yang menakutkan tersebut. Manusia mencoba menyangkal kefanaan dirinya dengan bersenang-senang, menenggelamkan diri dalam berbagai kesibukan, atau mencoba membuat berbagai monumen yang akan mengingatkan orang akan keberadaan dirinya. Orang pandai dan bijaksana mencoba bergumul dengan masalah ini, mencari hikmat dan kebijaksanaan. Tetapi, sebagaimana ditemukan oleh sang Pengkhotbah, nasib orang pandir dan orang bijaksana sama saja. Semuanya akan mati. Yang ada menjadi tiada. Apapun langkah yang diambil manusia, tidak ada yang dapat menghindari ataupun menyangkal sengat maut tersebut. Segala penyangkalan tidak dapat menutupi kesadaran akan kematian yang memaksa masuk, dan kesadaran akan ketakterhindaran kematian tersebut adalah sumber dari segala kecemasan dan ketakutan.
Para filsuf modern dari aliran Eksistensialisme, seperti Jean Paul Sartre, Albert Camus, Paul Tillich, dll juga menggumuli masalah pergumulan keberadaan (being) vs. ketiadaan (nonbeing). Mereka mengatakan bahwa tanpa bisa memilih, manusia terlempar ke dalam dunia, dengan berbagai situasinya. Dan tanpa bisa memilih juga, semua orang akan berakhir keberadaannya di dalam ketiadaan. Sartre mengatakan bahwa manusia senantiasa menghidupi (menghayati) kematiannya; dan setiap detik hidupnya ia mematikan (menghabiskan) kehidupannya. Di dalam perjalanan keberadaan yang menuju ketiadaan tersebut, pergumulan antara keberadaan vs. ketiadaan berlangsung terus, di dalam berbagai dimensi dan perwujudan. Dan demikianlah eksistensi manusia mengada, sebagai hasil dialektika hidup vs. mati tersebut. Kesadaran akan eksistensi manusia yang rapuh itu tak dapat tidak menimbulkan rasa muak (nausea) dalam diri manusia. Tiada jalan keluar dari sana.
Dari mana penderitaan berasal?
Saat seseorang mengalami penderitaan dalam hidupnya, ia mencari berbagai penjelasan agar ia dapat memahami situasi yang dialaminya. Salah satu penjelasan yang paling populer adalah: penderitaan datang karena saya berdosa. Saat mengalami “kesialan” atau musibah, orang sering berkata bahwa Tuhan sedang menegurnya. Kemudian orang mencoba memperbaiki tingkah lakunya, melakukan ritual persembahan korban-korban, dan berharap kesialannya akan berakhir. Penjelasan ini memiliki dua kelemahan utama: 1)sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari bahwa penderitaan tidak menimpa orang yang berdosa, melainkan menimpa orang benar, yaitu orang yang telah mencoba yang terbaik untuk menjalankan hidupnya sesuai keyakinannya akan kebenaran. Sehingga, tidak benarlah dalil yang mengatakan bahwa penderitaan datang sebagai azab, karena seseorang telah berdosa. 2)Tuhan bukanlah penyebab penderitaan. Mana mungkin kita menyebutNya Maha Baik dan Maha Kasih kalau ternyata Tuhan senang menghukum dan mencobai manusia, apapun alasannya. Rasul Yakobus mengatakan bahwa,”Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata:”Pencobaan ini datang dari Allah!” Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa; dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut.” (Yak 1: 13-15)
Di jaman modern ini, pendapat yang senada dengan Rasul Yakobus dikemukakan pula oleh Sigmund Freud. Dalam psikologi Freud dikatakan bahwa keberadaan manusia adalah keberadaan yang berketubuhan, di mana melalui ketubuhannya manusia memaknai dunia. Freud mengatakan bahwa sifat dasar dari tubuh itu sendiri adalah kecenderungannya mencari kesenangan. Tubuh menghendaki kesenangan sebesar mungkin sekarang juga; dan ingin menghindari segala derita sekecil apapun. Hal ini disebutnya pleasure principle.
Dalam perjumpaannya dengan realitas, manusia menemukan bahwa keinginan dasarnya itu tidak dapat selalu dipenuhi, karena realitas bekerja dengan aturan lain. Di dalam realitas, siapa yang menghendaki kesenangan yang lebih besar harus mau menunda dan menahan keinginannya. Misalnya: orang yang ingin kaya, harus mau menunda keinginan sesaat untuk makan enak, dan menabung uangnya; mahasiswa yang ingin pandai harus menunda keinginannya untuk nongkrong dengan teman-temannya, dan belajar; dst. Hal ini disebut reality principle.
Jadi, keberadaan manusia itu sendiri memang cenderung untuk mengalami konflik, yaitu konflik antara hasrat-hasrat tubuh dengan realitas yang membatasi. Konflik inilah yang selalu membuat manusia menderita, yaitu ketika keinginannya tidak terpenuhi karena berbenturan dengan kenyataan. Oleh karena itu, Freud menjadi pesimis. Menurutnya, konflik, kecemasan dan penderitaan adalah bagian yang tak terhindarkan dari keberadaan manusia.
Mengapa Tuhan membiarkan penderitaan ada?
Pesimisme Freud dapat dimengerti, tetapi untunglah perkembangan-perkembangan baru dalam psikologi mengemukakan kemungkinan baru yang lebih memberikan harapan. Mazhab keempat dalam psikologi, yaitu Transpersonal psychology mengemukakan suatu dalil yang secara revolusioner mengubah paradigma tentang keberadaan manusia. Dalil itu mengatakan bahwa esensi manusia bukanlah tubuh (daging), melainkan pada mulanya adalah roh. Karena suatu proses yang disebut Involusi, roh kemudian menjadi daging. Dalam bahasa Fisika, kita dapat mengatakan bahwa Roh yang pada esensinya adalah energi, ditransformasikan menjadi massa, yaitu tubuh.
Oleh karena itu, tidak seperti pandangan Freud atau tokoh-tokoh Eksistensialisme yang pesimis tentang manusia, Transpersonal Psychology mengatakan bahwa manusia sejatinya adalah mahluk Rohani yang karena proses Involusi mendapatkan pengalaman Badani; dan melalui proses Evolusi akan kembali menjadi Rohani. Hal yang senada dikemukakan oleh Pierre Teilhard de Chardin yang mengemukakan bahwa sejak adanya manusia di bumi ini, muncul lapisan baru selain Biosphere (lapisan kehidupan biologis di muka bumi), yaitu Noosphere (lapisan kesadaran). Kesadaran manusia melalui proses Evolusi akan menjadi makin kompleks, hingga mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Proses Evolusi akan memuncak dalam penyatuan materi dan roh menjadi suatu Maha Kesadaran yang disebut Chardin sebagai Titik Omega. Bagi Chardin, titik Alpha yang menjadi awal mula segala ciptaan, dan titik Omega kemana semua ciptaan menuju, tidak lain adalah Kristus.
Bila kita menerima pandangan visioner Chardin, maka kita dapat melihat keberadaan manusia yang sementara di dunia ini dengan kacamata yang berbeda. Keberadaan manusia di dunia bukan sekedar suatu kecelakaan akibat mutasi acak Evolusi, atau suatu ke-terlemparan ke dalam kehidupan; keberadaan manusia di dunia tidak dilalui dalam kesendirian melalui perjalanan panjang penuh derita menuju kematian. Keberadaan manusia di dunia adalah suatu perjalanan pulang kepada asalnya yang sejati, yaitu kebersatuan dengan Tuhannya di dalam Kekekalan. Di dalam paradigma ini, penderitaan di dalam hidup manusia tidak disangkal, tetapi dimaknai secara berbeda. Penderitaan bukanlah proses menuju kematian, tetapi kondisi tak terhindarkan dalam proses kelahiran kembali. Seperti seorang ibu yang harus menelan banyak rasa sakit dalam persalinan, umat manusia pun harus didera banyak derita, di dalam kelahirannya kembali di dalam Roh.
Bagi umat Kristiani, bukti yang paling nyata untuk memberi kesaksian tentang kebenaran itu, hadir di dalam diri Yesus Kristus, sang Anak Manusia. Ia yang berasal dari Allah, menjalani hidup penuh sengsara, memikul salib derita, mati dan kemudian bangkit kembali. Dengan demikian, pertanyaan mengapa Tuhan membiarkan adanya penderitaan di dunia ini terjawab sudah. Penderitaan memang harus ada di dalam proses kelahiran kembali umat manusia, dan bukan manusia yang menjadi Subjek utama penanggung derita, melainkan Tuhan sendiri di dalam diri Yesus Kristus. Manusia diundang untuk berpartisipasi di dalamnya, turut memikul salibNya agar bangkit pula bersamaNya.
Selamat menjalani pantang dan puasa..
Iman Setiadi Arif
Staff pengajar di Fakultas Psikologi Ukrida – Jakarta.
Tulisan ini pernah dimuat di Harian Suara Pembaruan
Bila kita membaca koran setiap harinya, satu yang tak akan lepas adalah membaca tentang berbagai wajah penderitaan di muka bumi. Puluhan ribu orang yang mati di Irak, ratusan ribu nyawa melayang karena Tsunami di Aceh, kekerasan di Poso, korban banjir di Jabodetabek, kriminalitas sehari-hari, dan berbagai penderitaan lain yang dialami secara solitaire tanpa diketahui orang banyak. Penderitaan kerap singgah dalam hidup setiap manusia, dan ketika penderitaan menghampiri hidupnya, orang pun bertanya,”Mengapa Tuhan membiarkan adanya penderitaan?”
Pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2007 ini, umat Kristiani memasuki hari Rabu Abu, yaitu dimulainya masa pantang dan puasa selama 40 hari untuk memperingati sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Puncak dari perayaan ini adalah pada hari tri hari suci, yaitu Kamis Putih, Jum’at Agung dan hari raya Paskah, yaitu perayaan kebangkitan Yesus Kristus dari alam maut. Di masa pantang dan puasa ini, umat Kristiani diajak untuk merenungkan misteri terbesar dalam kehidupan, yaitu bahwa hidup manusia di dunia niscaya adalah jalan penderitaan (via dolorosa) menuju kematian.
Dialektika keberadaan vs. ketiadaan
Pernyataan bahwa hidup adalah suatu perjalanan penuh derita menuju kematian, tampaknya sangat suram dan menyesakkan; tetapi hal itu adalah kebenaran mutlak yang tak dapat disangkal. Tiada kebenaran lain yang lebih mengguncang kenyamanan semu hidup manusia daripada penderitaan dan kematian. Dalam riwayat hidup Siddhartha Gautama, perjumpaannya dengan penderitaan dan kematianlah yang mengguncangkan dunia kesadarannya yang semu dan membuatnya menempuh perjalanan panjang menuju pembebasan, menjadi sang Buddha.
Pada umumnya manusia berusaha menyangkal kenyataan telanjang yang menakutkan tersebut. Manusia mencoba menyangkal kefanaan dirinya dengan bersenang-senang, menenggelamkan diri dalam berbagai kesibukan, atau mencoba membuat berbagai monumen yang akan mengingatkan orang akan keberadaan dirinya. Orang pandai dan bijaksana mencoba bergumul dengan masalah ini, mencari hikmat dan kebijaksanaan. Tetapi, sebagaimana ditemukan oleh sang Pengkhotbah, nasib orang pandir dan orang bijaksana sama saja. Semuanya akan mati. Yang ada menjadi tiada. Apapun langkah yang diambil manusia, tidak ada yang dapat menghindari ataupun menyangkal sengat maut tersebut. Segala penyangkalan tidak dapat menutupi kesadaran akan kematian yang memaksa masuk, dan kesadaran akan ketakterhindaran kematian tersebut adalah sumber dari segala kecemasan dan ketakutan.
Para filsuf modern dari aliran Eksistensialisme, seperti Jean Paul Sartre, Albert Camus, Paul Tillich, dll juga menggumuli masalah pergumulan keberadaan (being) vs. ketiadaan (nonbeing). Mereka mengatakan bahwa tanpa bisa memilih, manusia terlempar ke dalam dunia, dengan berbagai situasinya. Dan tanpa bisa memilih juga, semua orang akan berakhir keberadaannya di dalam ketiadaan. Sartre mengatakan bahwa manusia senantiasa menghidupi (menghayati) kematiannya; dan setiap detik hidupnya ia mematikan (menghabiskan) kehidupannya. Di dalam perjalanan keberadaan yang menuju ketiadaan tersebut, pergumulan antara keberadaan vs. ketiadaan berlangsung terus, di dalam berbagai dimensi dan perwujudan. Dan demikianlah eksistensi manusia mengada, sebagai hasil dialektika hidup vs. mati tersebut. Kesadaran akan eksistensi manusia yang rapuh itu tak dapat tidak menimbulkan rasa muak (nausea) dalam diri manusia. Tiada jalan keluar dari sana.
Dari mana penderitaan berasal?
Saat seseorang mengalami penderitaan dalam hidupnya, ia mencari berbagai penjelasan agar ia dapat memahami situasi yang dialaminya. Salah satu penjelasan yang paling populer adalah: penderitaan datang karena saya berdosa. Saat mengalami “kesialan” atau musibah, orang sering berkata bahwa Tuhan sedang menegurnya. Kemudian orang mencoba memperbaiki tingkah lakunya, melakukan ritual persembahan korban-korban, dan berharap kesialannya akan berakhir. Penjelasan ini memiliki dua kelemahan utama: 1)sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari bahwa penderitaan tidak menimpa orang yang berdosa, melainkan menimpa orang benar, yaitu orang yang telah mencoba yang terbaik untuk menjalankan hidupnya sesuai keyakinannya akan kebenaran. Sehingga, tidak benarlah dalil yang mengatakan bahwa penderitaan datang sebagai azab, karena seseorang telah berdosa. 2)Tuhan bukanlah penyebab penderitaan. Mana mungkin kita menyebutNya Maha Baik dan Maha Kasih kalau ternyata Tuhan senang menghukum dan mencobai manusia, apapun alasannya. Rasul Yakobus mengatakan bahwa,”Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata:”Pencobaan ini datang dari Allah!” Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa; dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut.” (Yak 1: 13-15)
Di jaman modern ini, pendapat yang senada dengan Rasul Yakobus dikemukakan pula oleh Sigmund Freud. Dalam psikologi Freud dikatakan bahwa keberadaan manusia adalah keberadaan yang berketubuhan, di mana melalui ketubuhannya manusia memaknai dunia. Freud mengatakan bahwa sifat dasar dari tubuh itu sendiri adalah kecenderungannya mencari kesenangan. Tubuh menghendaki kesenangan sebesar mungkin sekarang juga; dan ingin menghindari segala derita sekecil apapun. Hal ini disebutnya pleasure principle.
Dalam perjumpaannya dengan realitas, manusia menemukan bahwa keinginan dasarnya itu tidak dapat selalu dipenuhi, karena realitas bekerja dengan aturan lain. Di dalam realitas, siapa yang menghendaki kesenangan yang lebih besar harus mau menunda dan menahan keinginannya. Misalnya: orang yang ingin kaya, harus mau menunda keinginan sesaat untuk makan enak, dan menabung uangnya; mahasiswa yang ingin pandai harus menunda keinginannya untuk nongkrong dengan teman-temannya, dan belajar; dst. Hal ini disebut reality principle.
Jadi, keberadaan manusia itu sendiri memang cenderung untuk mengalami konflik, yaitu konflik antara hasrat-hasrat tubuh dengan realitas yang membatasi. Konflik inilah yang selalu membuat manusia menderita, yaitu ketika keinginannya tidak terpenuhi karena berbenturan dengan kenyataan. Oleh karena itu, Freud menjadi pesimis. Menurutnya, konflik, kecemasan dan penderitaan adalah bagian yang tak terhindarkan dari keberadaan manusia.
Mengapa Tuhan membiarkan penderitaan ada?
Pesimisme Freud dapat dimengerti, tetapi untunglah perkembangan-perkembangan baru dalam psikologi mengemukakan kemungkinan baru yang lebih memberikan harapan. Mazhab keempat dalam psikologi, yaitu Transpersonal psychology mengemukakan suatu dalil yang secara revolusioner mengubah paradigma tentang keberadaan manusia. Dalil itu mengatakan bahwa esensi manusia bukanlah tubuh (daging), melainkan pada mulanya adalah roh. Karena suatu proses yang disebut Involusi, roh kemudian menjadi daging. Dalam bahasa Fisika, kita dapat mengatakan bahwa Roh yang pada esensinya adalah energi, ditransformasikan menjadi massa, yaitu tubuh.
Oleh karena itu, tidak seperti pandangan Freud atau tokoh-tokoh Eksistensialisme yang pesimis tentang manusia, Transpersonal Psychology mengatakan bahwa manusia sejatinya adalah mahluk Rohani yang karena proses Involusi mendapatkan pengalaman Badani; dan melalui proses Evolusi akan kembali menjadi Rohani. Hal yang senada dikemukakan oleh Pierre Teilhard de Chardin yang mengemukakan bahwa sejak adanya manusia di bumi ini, muncul lapisan baru selain Biosphere (lapisan kehidupan biologis di muka bumi), yaitu Noosphere (lapisan kesadaran). Kesadaran manusia melalui proses Evolusi akan menjadi makin kompleks, hingga mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Proses Evolusi akan memuncak dalam penyatuan materi dan roh menjadi suatu Maha Kesadaran yang disebut Chardin sebagai Titik Omega. Bagi Chardin, titik Alpha yang menjadi awal mula segala ciptaan, dan titik Omega kemana semua ciptaan menuju, tidak lain adalah Kristus.
Bila kita menerima pandangan visioner Chardin, maka kita dapat melihat keberadaan manusia yang sementara di dunia ini dengan kacamata yang berbeda. Keberadaan manusia di dunia bukan sekedar suatu kecelakaan akibat mutasi acak Evolusi, atau suatu ke-terlemparan ke dalam kehidupan; keberadaan manusia di dunia tidak dilalui dalam kesendirian melalui perjalanan panjang penuh derita menuju kematian. Keberadaan manusia di dunia adalah suatu perjalanan pulang kepada asalnya yang sejati, yaitu kebersatuan dengan Tuhannya di dalam Kekekalan. Di dalam paradigma ini, penderitaan di dalam hidup manusia tidak disangkal, tetapi dimaknai secara berbeda. Penderitaan bukanlah proses menuju kematian, tetapi kondisi tak terhindarkan dalam proses kelahiran kembali. Seperti seorang ibu yang harus menelan banyak rasa sakit dalam persalinan, umat manusia pun harus didera banyak derita, di dalam kelahirannya kembali di dalam Roh.
Bagi umat Kristiani, bukti yang paling nyata untuk memberi kesaksian tentang kebenaran itu, hadir di dalam diri Yesus Kristus, sang Anak Manusia. Ia yang berasal dari Allah, menjalani hidup penuh sengsara, memikul salib derita, mati dan kemudian bangkit kembali. Dengan demikian, pertanyaan mengapa Tuhan membiarkan adanya penderitaan di dunia ini terjawab sudah. Penderitaan memang harus ada di dalam proses kelahiran kembali umat manusia, dan bukan manusia yang menjadi Subjek utama penanggung derita, melainkan Tuhan sendiri di dalam diri Yesus Kristus. Manusia diundang untuk berpartisipasi di dalamnya, turut memikul salibNya agar bangkit pula bersamaNya.
Selamat menjalani pantang dan puasa..
Iman Setiadi Arif
Staff pengajar di Fakultas Psikologi Ukrida – Jakarta.
Pengecut..
Pengecut…
Tulisan ini pernah dimuat di Harian Suara Pembaruan
Beberapa waktu yang lalu, penulis menghadiri misa Requiem salah seorang jemaat Gereja penulis, yang menjadi korban dalam kecelakaan pesawat Garuda di Jogjakarta. Misa tersebut dilaksanakan dengan sangat indah dan mengharukan, sehingga kebanyakan peserta meneteskan air mata dalam keharuan bersama. Setelah perwakilan keluarga menyampaikan ucapan terakhir yang sangat menyentuh tentang almarhumah, giliran kesaksian dari salah seorang kerabat yang juga turut dalam penerbangan tersebut, namun luput dari maut. Kesaksiannya memberikan insight bagi penulis, dan dalam kesempatan ini ingin penulis bagikan kepada para pembaca.
Indra (bukan nama sesungguhnya) terbang bersama ipar perempuannya ke Jogjakarta, di dalam pesawat Garuda yang naas tersebut. Ia menceritakan bahwa saat menjadi jelas bagi para penumpang bahwa pesawat sedang meluncur tak terkendali, kepanikan melanda. Kebanyakan penumpang menjerit, dan sebagian lagi berseru kepada Tuhan menurut cara agamanya masing-masing. Suatu fenomena yang unik dialami Indra. Saat detik-detik kritis itu berlangsung – dan segala sesuatu berlangsung dengan begitu cepat – Indra merasakan segala sesuatu berjalan dalam slow motion. Ia sendiri sangat heran bahwa dalam situasi paling genting tersebut ia dapat menyaksikan segala sesuatunya dengan sangat jelas. Aneh tapi nyata, bila pada kebanyakan orang dalam situasi tersebut, kesadaran akan menyusut bahkan sampai hilang (pingsan); Indra merasakan suatu konsentrasi kesadaran yang belum pernah dialaminya, sehingga segala sesuatu menjadi sangat jelas disaksikannya.
Setelah pesawat meledak dan mulai terbakar, orang-orang berlomba-lomba menyelamatkan diri. Saat itu Indra dihadapkan pada pilihan tersulit dalam hidupnya. Ia duduk dekat pintu keluar sehingga dapat dengan segera menyelamatkan diri; tetapi iparnya duduk jauh di depan, di mana api dan asap telah menutupi pandangan. Indra harus memilih, apakah ia akan menyelamatkan diri segera – atau mencoba menyelamatkan iparnya yang kemungkinan besar terjebak di barisan depan. Tidak ada banyak waktu untuk berpikir, tidak ada orang lain untuk diminta pendapatnya, bahkan Indra merasakan bahwa Tuhan diam dan tidak memberikan petunjuk pilihan mana yang harus diambilnya. Pilihan harus dibuatnya segera, sendiri. Indra memilih untuk keluar, menyelamatkan diri. Sambil melakukannya, hatinya dihunjam rasa bersalah dan cela diri. Suara hatinya terdengar jelas,”Aku seorang pengecut!! Seharusnya aku menyelamatkan iparku yang mungkin terpanggang api di sana..”
Dinamika intrapsikis yang dialami Indra seolah membenarkan pendapat Sigmund Freud tentang hakikat manusia. Ia mengatakan bahwa manusia pada dasarnya bersifat narcissistic. Di lubuk hatinya yang paling dalam, manusia hanya mementingkan dirinya sendiri dan menomorsatukan keselamatannya sendiri. Saat tekanan menjadi terlalu besar, Ego hancur dan suara Superego diabaikan. Yang meraja adalah Insting dasar yang irasional: Self-preservation, yaitu bagian dari Insting hidup yang bersifat biologis, untuk survive. Maka tidak heran kalau Freud bersikap pessimistic tentang kemanusiaan.
Indra berjalan dengan penuh sesal diri di pesawahan di mana sebagian korban yang selamat terbaring luka-luka. Di sana ia melihat…iparnya terbaring dengan hanya luka-luka ringan. Suatu petir menyambar benak Indra. Ia baru saja merasa gagal menghadapi “ujian” moral dan iman ketika menghadapi pilihan antara hidup dan mati tersebut. Ia telah melakukan pilihan yang keliru secara moral, yaitu memilih untuk bersikap pengecut, menyelamatkan dirinya sendiri, tidak menolong iparnya. Absurdnya adalah: rupanya pilihannya tepat. Karena kalau ia mengikuti dorongan rasa bersalahnya untuk memaksakan diri menyelamatkan iparnya, maka kemungkinan besar ia akan turut terpanggang di dalam pesawat, sementara iparnya sesungguhnya sudah selamat di luar. Mana yang benar? Mana yang salah? Pilihannya yang salah secara moral, telah membawanya pada jalan hidup.
Para pembaca yang budiman, mohon jangan salah tangkap. Pesan dalam cerita yang ingin penulis bagikan melalui cerita di atas tentunya bukan suatu seruan untuk mengesampingkan pertimbangan moral dan mengambil sikap SDM (Selamatkan Diri Masing-masing). Tetapi, seperti Indra yang bersaksi dengan penuh ketakjuban akan misteri Ilahi, penulis pun hendak mengajak para pembaca masuk dalam misteri hidup ini.
Dalam menjalani keberadaan kita yang rapuh di dunia ini, berkali-kali kita dihadapkan pada persimpangan jalan. Seperti Indra, kita pun seringkali harus segera membuat keputusan seorang diri, tanpa cukup informasi untuk mengambil keputusan yang bijaksana. Tiada orang untuk bertanya, dan Tuhan pun “diam”. Dan seperti Indra, kita pun berkali-kali sudah membuat keputusan-keputusan yang keliru. Barangkali kitapun malu pada diri sendiri karena terbukti tidak punya cukup nyali dan tidak dapat mengambil keputusan yang heroic dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang sering kita khotbahkan. Tapi inilah misterinya: Tuhan rupanya tidak selalu menggunakan kekuatan, keberanian dan kebenaran dalam diri seorang manusia untuk mencapai maksudNya. Tuhan pun kadang menggunakan kelemahan dan kesalahan manusia.
Kira-kira dua ribu tahun yang lalu, seorang murid Yesus yang dipandangNya paling kuat karakternya, sehingga diberi nama julukan “batu karang”, juga melakukan kesalahan yang sama. Petrus yang berkoar akan mati bersama-sama Yesus, ternyata hancur nyalinya di detik-detik yang paling menentukan. Ia menyangkal Yesus sampai tiga kali, untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dan ketika ia memandang wajah Yesus setelah penyangkalannya yang ketiga, ia menangis dengan sedihnya karena ia sadar betapa pengecutnya dirinya. Tetapi misterinya adalah: Tuhan membentuk karakter Petrus bukan dengan menunjukkan ketegaran dan keheroikan dirinya, tapi justru dengan membawa Petrus ke titik nadir konsep dirinya. Petrus dihadapkan pada wajah karakternya yang sesungguhnya; dan wajah itu buruk rupa: Petrus adalah seorang pengecut. Gambaran dirinya yang ideal hancur. Namun, dari puing-puing konsep diri inilah Yesus membentuk seorang Rasul yang gagah berani dan kelak menjadi martirnya dengan disalib terbalik, menjadi fondasi Gereja. Saya berpikir, seandainya Petrus bersikap gagah perkasa saat Yesus ditangkap, barangkali Yesus akan senang karena Petrus sudah bersikap baik dan benar; namun Yesus pun akan kehilangan salah seorang saksiNya yang paling berharga kelak.
Buat saya, insight di atas menjadi suatu kabar baik yang membebaskan. Yesus memang memerintahkan kita untuk menjadi sempurna, sama seperti Bapa di Sorga juga sempurna. Tetapi, Yesus pun mengenal hati manusia, karena Ia yang menciptakan kita. Konsep Yesus tentang kesempurnaan, rupanya masih memberi ruang untuk kesalahan dan kemanusiawian. Ketika Yesus bertemu lagi dengan Petrus sesudah kebangkitanNya, Ia tidak bertanya,”Simon, anak Yohanes, apakah engkau sudah menjadi berani dan sempurna sekarang?” Ia bertanya,”Simon, anak Yohanes, apakah engkau mencintai Aku?” Dan Ia mendirikan GerejaNya bukan dengan sekumpulan hero yang adimanusiawi, melainkan dari sekumpulan manusia yang sekalipun kadang lemah, namun sungguh-sungguh mencintaiNya.
Cintalah yang pada akhirnya menjadi ukuran. Melalui mata cinta, kita dapat memandang melampaui batasan ketidaksempurnaan diri dan sesama, melampaui absurditas dan keirasionalan hidup ini. Di dalam Cinta, selalu ada harapan. Cinta mengatasi segala-galanya dan hanya di dalam Cinta-lah Kerajaan Allah dapat didirikan.
Iman Setiadi Arif
Staf pengajar Fakultas Psikologi Ukrida – Jakarta
Tulisan ini pernah dimuat di Harian Suara Pembaruan
Beberapa waktu yang lalu, penulis menghadiri misa Requiem salah seorang jemaat Gereja penulis, yang menjadi korban dalam kecelakaan pesawat Garuda di Jogjakarta. Misa tersebut dilaksanakan dengan sangat indah dan mengharukan, sehingga kebanyakan peserta meneteskan air mata dalam keharuan bersama. Setelah perwakilan keluarga menyampaikan ucapan terakhir yang sangat menyentuh tentang almarhumah, giliran kesaksian dari salah seorang kerabat yang juga turut dalam penerbangan tersebut, namun luput dari maut. Kesaksiannya memberikan insight bagi penulis, dan dalam kesempatan ini ingin penulis bagikan kepada para pembaca.
Indra (bukan nama sesungguhnya) terbang bersama ipar perempuannya ke Jogjakarta, di dalam pesawat Garuda yang naas tersebut. Ia menceritakan bahwa saat menjadi jelas bagi para penumpang bahwa pesawat sedang meluncur tak terkendali, kepanikan melanda. Kebanyakan penumpang menjerit, dan sebagian lagi berseru kepada Tuhan menurut cara agamanya masing-masing. Suatu fenomena yang unik dialami Indra. Saat detik-detik kritis itu berlangsung – dan segala sesuatu berlangsung dengan begitu cepat – Indra merasakan segala sesuatu berjalan dalam slow motion. Ia sendiri sangat heran bahwa dalam situasi paling genting tersebut ia dapat menyaksikan segala sesuatunya dengan sangat jelas. Aneh tapi nyata, bila pada kebanyakan orang dalam situasi tersebut, kesadaran akan menyusut bahkan sampai hilang (pingsan); Indra merasakan suatu konsentrasi kesadaran yang belum pernah dialaminya, sehingga segala sesuatu menjadi sangat jelas disaksikannya.
Setelah pesawat meledak dan mulai terbakar, orang-orang berlomba-lomba menyelamatkan diri. Saat itu Indra dihadapkan pada pilihan tersulit dalam hidupnya. Ia duduk dekat pintu keluar sehingga dapat dengan segera menyelamatkan diri; tetapi iparnya duduk jauh di depan, di mana api dan asap telah menutupi pandangan. Indra harus memilih, apakah ia akan menyelamatkan diri segera – atau mencoba menyelamatkan iparnya yang kemungkinan besar terjebak di barisan depan. Tidak ada banyak waktu untuk berpikir, tidak ada orang lain untuk diminta pendapatnya, bahkan Indra merasakan bahwa Tuhan diam dan tidak memberikan petunjuk pilihan mana yang harus diambilnya. Pilihan harus dibuatnya segera, sendiri. Indra memilih untuk keluar, menyelamatkan diri. Sambil melakukannya, hatinya dihunjam rasa bersalah dan cela diri. Suara hatinya terdengar jelas,”Aku seorang pengecut!! Seharusnya aku menyelamatkan iparku yang mungkin terpanggang api di sana..”
Dinamika intrapsikis yang dialami Indra seolah membenarkan pendapat Sigmund Freud tentang hakikat manusia. Ia mengatakan bahwa manusia pada dasarnya bersifat narcissistic. Di lubuk hatinya yang paling dalam, manusia hanya mementingkan dirinya sendiri dan menomorsatukan keselamatannya sendiri. Saat tekanan menjadi terlalu besar, Ego hancur dan suara Superego diabaikan. Yang meraja adalah Insting dasar yang irasional: Self-preservation, yaitu bagian dari Insting hidup yang bersifat biologis, untuk survive. Maka tidak heran kalau Freud bersikap pessimistic tentang kemanusiaan.
Indra berjalan dengan penuh sesal diri di pesawahan di mana sebagian korban yang selamat terbaring luka-luka. Di sana ia melihat…iparnya terbaring dengan hanya luka-luka ringan. Suatu petir menyambar benak Indra. Ia baru saja merasa gagal menghadapi “ujian” moral dan iman ketika menghadapi pilihan antara hidup dan mati tersebut. Ia telah melakukan pilihan yang keliru secara moral, yaitu memilih untuk bersikap pengecut, menyelamatkan dirinya sendiri, tidak menolong iparnya. Absurdnya adalah: rupanya pilihannya tepat. Karena kalau ia mengikuti dorongan rasa bersalahnya untuk memaksakan diri menyelamatkan iparnya, maka kemungkinan besar ia akan turut terpanggang di dalam pesawat, sementara iparnya sesungguhnya sudah selamat di luar. Mana yang benar? Mana yang salah? Pilihannya yang salah secara moral, telah membawanya pada jalan hidup.
Para pembaca yang budiman, mohon jangan salah tangkap. Pesan dalam cerita yang ingin penulis bagikan melalui cerita di atas tentunya bukan suatu seruan untuk mengesampingkan pertimbangan moral dan mengambil sikap SDM (Selamatkan Diri Masing-masing). Tetapi, seperti Indra yang bersaksi dengan penuh ketakjuban akan misteri Ilahi, penulis pun hendak mengajak para pembaca masuk dalam misteri hidup ini.
Dalam menjalani keberadaan kita yang rapuh di dunia ini, berkali-kali kita dihadapkan pada persimpangan jalan. Seperti Indra, kita pun seringkali harus segera membuat keputusan seorang diri, tanpa cukup informasi untuk mengambil keputusan yang bijaksana. Tiada orang untuk bertanya, dan Tuhan pun “diam”. Dan seperti Indra, kita pun berkali-kali sudah membuat keputusan-keputusan yang keliru. Barangkali kitapun malu pada diri sendiri karena terbukti tidak punya cukup nyali dan tidak dapat mengambil keputusan yang heroic dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang sering kita khotbahkan. Tapi inilah misterinya: Tuhan rupanya tidak selalu menggunakan kekuatan, keberanian dan kebenaran dalam diri seorang manusia untuk mencapai maksudNya. Tuhan pun kadang menggunakan kelemahan dan kesalahan manusia.
Kira-kira dua ribu tahun yang lalu, seorang murid Yesus yang dipandangNya paling kuat karakternya, sehingga diberi nama julukan “batu karang”, juga melakukan kesalahan yang sama. Petrus yang berkoar akan mati bersama-sama Yesus, ternyata hancur nyalinya di detik-detik yang paling menentukan. Ia menyangkal Yesus sampai tiga kali, untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dan ketika ia memandang wajah Yesus setelah penyangkalannya yang ketiga, ia menangis dengan sedihnya karena ia sadar betapa pengecutnya dirinya. Tetapi misterinya adalah: Tuhan membentuk karakter Petrus bukan dengan menunjukkan ketegaran dan keheroikan dirinya, tapi justru dengan membawa Petrus ke titik nadir konsep dirinya. Petrus dihadapkan pada wajah karakternya yang sesungguhnya; dan wajah itu buruk rupa: Petrus adalah seorang pengecut. Gambaran dirinya yang ideal hancur. Namun, dari puing-puing konsep diri inilah Yesus membentuk seorang Rasul yang gagah berani dan kelak menjadi martirnya dengan disalib terbalik, menjadi fondasi Gereja. Saya berpikir, seandainya Petrus bersikap gagah perkasa saat Yesus ditangkap, barangkali Yesus akan senang karena Petrus sudah bersikap baik dan benar; namun Yesus pun akan kehilangan salah seorang saksiNya yang paling berharga kelak.
Buat saya, insight di atas menjadi suatu kabar baik yang membebaskan. Yesus memang memerintahkan kita untuk menjadi sempurna, sama seperti Bapa di Sorga juga sempurna. Tetapi, Yesus pun mengenal hati manusia, karena Ia yang menciptakan kita. Konsep Yesus tentang kesempurnaan, rupanya masih memberi ruang untuk kesalahan dan kemanusiawian. Ketika Yesus bertemu lagi dengan Petrus sesudah kebangkitanNya, Ia tidak bertanya,”Simon, anak Yohanes, apakah engkau sudah menjadi berani dan sempurna sekarang?” Ia bertanya,”Simon, anak Yohanes, apakah engkau mencintai Aku?” Dan Ia mendirikan GerejaNya bukan dengan sekumpulan hero yang adimanusiawi, melainkan dari sekumpulan manusia yang sekalipun kadang lemah, namun sungguh-sungguh mencintaiNya.
Cintalah yang pada akhirnya menjadi ukuran. Melalui mata cinta, kita dapat memandang melampaui batasan ketidaksempurnaan diri dan sesama, melampaui absurditas dan keirasionalan hidup ini. Di dalam Cinta, selalu ada harapan. Cinta mengatasi segala-galanya dan hanya di dalam Cinta-lah Kerajaan Allah dapat didirikan.
Iman Setiadi Arif
Staf pengajar Fakultas Psikologi Ukrida – Jakarta
Santai man...
Santai man…
Tulisan ini pernah dimuat di Harian Suara Pembaruan
Beberapa waktu yang lalu, diputar di bioskop-bioskop Jakarta, sebuah film komedi berjudul “Click!”. Tokoh utamanya diperankan oleh Adam Sandler. Sandler adalah seorang arsitek junior, yang tengah berjuang untuk meningkatkan karirnya di tengah persaingan yang sangat ketat dan tekanan kerja yang sangat berat. Seringkali ia harus mengorbankan waktunya untuk keluarga, agar dapat mengejar ambisinya untuk menjadi partner di dalam biro arsitek di tempatnya bekerja.
Dikisahkan bahwa Sandler kemudian diberi sebuah remote control ajaib, oleh seorang tokoh misterius yang diperankan oleh Christopher Walken. Tidak seperti remote control yang biasa, remote control ajaib ini dapat diarahkan pada sembarang benda, dan dapat mengendalikan benda tersebut, sebagaimana kita mengendalikan acara teve. Misalnya, Sandler dapat memperkecil volume suara gonggongan anjingnya yang berisik, dapat membuat boss-nya yang sedang mengomel berhenti, bahkan yang paling hebat adalah ia dapat memajukan (fast forwarding) waktu sekehendak hatinya. Bilamana ia sedang mengerjakan tugas yang membuatnya penat, ia dapat memajukan waktu sehingga tiba-tiba ia sudah berada di masa yang akan datang, di mana tugas tersebut telah selesai. Bilamana ia terjebak dalam kemacetan, ia pun tinggal memajukan waktu, sehingga tiba-tiba ia sudah berada di luar kemacetan.
Sandler merasa menjadi orang paling berbahagia di dunia dengan remote control ajaibnya ini; sampai ia mulai merasakan, bahwa lama kelamaan, bukan lagi dirinya yang mengendalikan remote control tersebut, melainkan remote control itu yang mengendalikan hidupnya. Remote control tersebut mulai bekerja secara otomatis, mengikuti pola kebiasaan Sandler selama ini. Ia selalu mempercepat waktu – tanpa diperintahkan lagi oleh Sandler – sehingga Sandler melewatkan bukan hanya hal-hal yang menyebalkannya, tetapi juga waktu-waktu yang paling bermakna dalam hidupnya. Tiba-tiba Sandler sudah menjadi partner senior di biro arsiteknya; tiba-tiba anak-anaknya sudah besar, tanpa Sandler dapat mengikuti perkembangannya dan menikmati perannya sebagai ayah bagi kedua anaknya; tiba-tiba ia sudah menjadi Arsitek yang super sukses, namun sekaligus sudah tua dan penyakitan, dan telah bercerai dengan istrinya. Sandler mencapai segala ambisinya – bahkan lebih dari itu – namun dengan pengorbanan yang mengerikan: ia tidak pernah dapat mengecap hidup yang dihabiskannya dengan begitu cepat.
Generasi yang diburu waktu
Film “Click!” adalah sebuah parodi tentang kehidupan di kota besar. Ia bicara tentang sebuah generasi yang diburu waktu. Semua orang di segala usia dituntut untuk melakukan lebih banyak hal, mencapai prestasi yang lebih baik lagi dan melakukan segala sesuatu dengan secepat mungkin. Para motivator terus menerus menanamkan ide di kepala kita, bahwa jangan pernah kita merasa puas, melainkan kita harus terus merasa haus untuk mendapatkan lebih banyak lagi dari hidup ini. Orang jadi merasa bersalah kalau ia tidak sibuk dan tergoda untuk bersantai sedikit saja. Sekarang kita sudah biasa melihat anak SD - atau bahkan TK - yang mendorong tasnya yang penuh sesak dengan buku, dari satu tempat kursus ke tempat kursus yang lain. Bilamana anak berusia 1 tahun baru dapat mengucapkan satu dua patah kata, orangtuanya sudah khawatir bahwa anaknya menderita autism dan segera membawa anaknya ke tempat speech therapy. Kursus untuk membaca dan menghitung cepat, laris manis diikuti orang-orang dari pelbagai usia. Singkat kata, seperti Adam Sandler di film “Click!” kita selalu memfast-forward hidup kita, sampai hidup itu habis tanpa kita sempat mengecapnya.
Kerinduan untuk mengecap kehidupan
Di lubuk hati orang-orang modern, tersimpan kerinduan untuk mengecap kehidupan. Mulai terbit kesadaran bahwa bekerja lebih keras dan memperoleh materi lebih banyak lagi, tidak dengan sendirinya membawa kebahagiaan. Namun, belenggu kebiasaan dan tekanan masyarakat yang sangat kuat kadang terlalu kuat untuk ditolak.
Berikut adalah beberapa teknik yang dikembangkan oleh psikologi modern untuk mematahkan belenggu dan tekanan itu dan mulai mengecap anugerah kehidupan yang diberikan kepada kita.
Savoring
Salah satu cara untuk berbahagia adalah dengan hidup di saat ini. Fred B. Bryant dan Joseph Veroff dari Loyola University adalah para psikolog yang mengembangkan konsep yang disebut Savoring. Savoring berarti kesadaran penuh akan kesenangan yang dialami saat ini, dan dengan sengaja memusatkan perhatian pada perasaan itu dan menikmatinya selagi berlangsung.
Mereka mengajar para siswanya untuk berlatih Savoring dengan cara meluangkan waktu untuk melakukan salah satu kegiatan yang disukai, dan memusatkan perhatian pada kegiatan itu saja. Misalnya: seorang siswa memilih untuk membaca puisi yang disukainya. Siswa itu dianjurkan untuk membaca kata demi kata dalam puisi tersebut dengan penuh perhatian, membiarkan kata-kata itu mengalir tanpa terburu-buru dan meresapi diri mereka perlahan-lahan. Saat orang melakukan Savoring, waktu berlalu tanpa terasa – namun setiap detik dihayati dengan penuh. Orang akan merasakan kelegaan dan kedamaian yang belum pernah dirasakannya, dan tidak jarang hatinya meluap dengan kebahagiaan. Orang belajar untuk merasa cukup dan puas dengan yang dimilikinya saat ini.
Bukan lebih banyak, tapi lebih bermakna
Hambatan terbesar untuk menikmati hidup dengan penuh berasal dari diri sendiri. Hambatan itu berupa pikiran irasional yang meyakini bahwa bila anda lambat, maka anda akan tertinggal dan terlindas. Bila anda tidak serakah, anda tidak akan kebagian. Bila anda mendapatkan lebih banyak, maka anda akan lebih bahagia. Pikiran-pikiran ini disebut irasional, karena sebenarnya tidak ada bukti yang kuat yang mendasarinya, namun kita toh meyakininya dengan membuta. Kalaupun kita menyadari bahwa pikiran itu keliru, seringkali kita tidak cukup kuat untuk melawannya. Kita telah terbiasa untuk mengikuti pikiran irasional tersebut, karena takut bila tidak mengikutinya maka suatu hal buruk akan menimpa kita.
Pikiran irasional mesti digantikan dengan pikiran rasional. Pikiran rasional berdasarkan pada bukti di kenyataan dan membantu kita menyesuaikan diri lebih baik. Seorang psikolog terkemuka bernama Mihaly Csikszentmihalyi telah melakukan penelitian pada orang-orang yang paling sukses dan paling kreatif di bidangnya masing-masing, misalnya: Atlet peraih emas Olimpiade, Ilmuwan peraih Nobel, Artis peraih Oscar. Penelitiannya menunjukkan bahwa faktor yang terpenting pada keberhasilan mereka bukanlah kerja sekeras mungkin untuk meraih sebanyak mungkin – sungguhpun mereka harus bekerja keras – melainkan kerja dengan suatu keasyikan untuk melakukan sesuatu yang bermakna. Mengerjakan sesuatu yang bermakna dengan penuh keasyikan disebut Csikszentmihalyi dengan istilah Flow. Orang-orang yang sungguh sukses, justru telah belajar bagaimana untuk meredakan dorongan hati yang serakah untuk meraih semuanya, melainkan fokus pada sedikit hal saja yang bermakna. They do less, so they can do better.
Oleh karena itu, marilah kita menjalani dan menikmati hidup kita, pekerjaan kita, relasi kita dengan keluarga dan teman dengan penuh keasyikan, dan rasa syukur. Waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali, maka nikmatilah saat ini sepenuhnya. Santai man…
Iman Setiadi Arif
Dekan Fakultas Psikologi Ukrida – Jakarta
Tulisan ini pernah dimuat di Harian Suara Pembaruan
Beberapa waktu yang lalu, diputar di bioskop-bioskop Jakarta, sebuah film komedi berjudul “Click!”. Tokoh utamanya diperankan oleh Adam Sandler. Sandler adalah seorang arsitek junior, yang tengah berjuang untuk meningkatkan karirnya di tengah persaingan yang sangat ketat dan tekanan kerja yang sangat berat. Seringkali ia harus mengorbankan waktunya untuk keluarga, agar dapat mengejar ambisinya untuk menjadi partner di dalam biro arsitek di tempatnya bekerja.
Dikisahkan bahwa Sandler kemudian diberi sebuah remote control ajaib, oleh seorang tokoh misterius yang diperankan oleh Christopher Walken. Tidak seperti remote control yang biasa, remote control ajaib ini dapat diarahkan pada sembarang benda, dan dapat mengendalikan benda tersebut, sebagaimana kita mengendalikan acara teve. Misalnya, Sandler dapat memperkecil volume suara gonggongan anjingnya yang berisik, dapat membuat boss-nya yang sedang mengomel berhenti, bahkan yang paling hebat adalah ia dapat memajukan (fast forwarding) waktu sekehendak hatinya. Bilamana ia sedang mengerjakan tugas yang membuatnya penat, ia dapat memajukan waktu sehingga tiba-tiba ia sudah berada di masa yang akan datang, di mana tugas tersebut telah selesai. Bilamana ia terjebak dalam kemacetan, ia pun tinggal memajukan waktu, sehingga tiba-tiba ia sudah berada di luar kemacetan.
Sandler merasa menjadi orang paling berbahagia di dunia dengan remote control ajaibnya ini; sampai ia mulai merasakan, bahwa lama kelamaan, bukan lagi dirinya yang mengendalikan remote control tersebut, melainkan remote control itu yang mengendalikan hidupnya. Remote control tersebut mulai bekerja secara otomatis, mengikuti pola kebiasaan Sandler selama ini. Ia selalu mempercepat waktu – tanpa diperintahkan lagi oleh Sandler – sehingga Sandler melewatkan bukan hanya hal-hal yang menyebalkannya, tetapi juga waktu-waktu yang paling bermakna dalam hidupnya. Tiba-tiba Sandler sudah menjadi partner senior di biro arsiteknya; tiba-tiba anak-anaknya sudah besar, tanpa Sandler dapat mengikuti perkembangannya dan menikmati perannya sebagai ayah bagi kedua anaknya; tiba-tiba ia sudah menjadi Arsitek yang super sukses, namun sekaligus sudah tua dan penyakitan, dan telah bercerai dengan istrinya. Sandler mencapai segala ambisinya – bahkan lebih dari itu – namun dengan pengorbanan yang mengerikan: ia tidak pernah dapat mengecap hidup yang dihabiskannya dengan begitu cepat.
Generasi yang diburu waktu
Film “Click!” adalah sebuah parodi tentang kehidupan di kota besar. Ia bicara tentang sebuah generasi yang diburu waktu. Semua orang di segala usia dituntut untuk melakukan lebih banyak hal, mencapai prestasi yang lebih baik lagi dan melakukan segala sesuatu dengan secepat mungkin. Para motivator terus menerus menanamkan ide di kepala kita, bahwa jangan pernah kita merasa puas, melainkan kita harus terus merasa haus untuk mendapatkan lebih banyak lagi dari hidup ini. Orang jadi merasa bersalah kalau ia tidak sibuk dan tergoda untuk bersantai sedikit saja. Sekarang kita sudah biasa melihat anak SD - atau bahkan TK - yang mendorong tasnya yang penuh sesak dengan buku, dari satu tempat kursus ke tempat kursus yang lain. Bilamana anak berusia 1 tahun baru dapat mengucapkan satu dua patah kata, orangtuanya sudah khawatir bahwa anaknya menderita autism dan segera membawa anaknya ke tempat speech therapy. Kursus untuk membaca dan menghitung cepat, laris manis diikuti orang-orang dari pelbagai usia. Singkat kata, seperti Adam Sandler di film “Click!” kita selalu memfast-forward hidup kita, sampai hidup itu habis tanpa kita sempat mengecapnya.
Kerinduan untuk mengecap kehidupan
Di lubuk hati orang-orang modern, tersimpan kerinduan untuk mengecap kehidupan. Mulai terbit kesadaran bahwa bekerja lebih keras dan memperoleh materi lebih banyak lagi, tidak dengan sendirinya membawa kebahagiaan. Namun, belenggu kebiasaan dan tekanan masyarakat yang sangat kuat kadang terlalu kuat untuk ditolak.
Berikut adalah beberapa teknik yang dikembangkan oleh psikologi modern untuk mematahkan belenggu dan tekanan itu dan mulai mengecap anugerah kehidupan yang diberikan kepada kita.
Savoring
Salah satu cara untuk berbahagia adalah dengan hidup di saat ini. Fred B. Bryant dan Joseph Veroff dari Loyola University adalah para psikolog yang mengembangkan konsep yang disebut Savoring. Savoring berarti kesadaran penuh akan kesenangan yang dialami saat ini, dan dengan sengaja memusatkan perhatian pada perasaan itu dan menikmatinya selagi berlangsung.
Mereka mengajar para siswanya untuk berlatih Savoring dengan cara meluangkan waktu untuk melakukan salah satu kegiatan yang disukai, dan memusatkan perhatian pada kegiatan itu saja. Misalnya: seorang siswa memilih untuk membaca puisi yang disukainya. Siswa itu dianjurkan untuk membaca kata demi kata dalam puisi tersebut dengan penuh perhatian, membiarkan kata-kata itu mengalir tanpa terburu-buru dan meresapi diri mereka perlahan-lahan. Saat orang melakukan Savoring, waktu berlalu tanpa terasa – namun setiap detik dihayati dengan penuh. Orang akan merasakan kelegaan dan kedamaian yang belum pernah dirasakannya, dan tidak jarang hatinya meluap dengan kebahagiaan. Orang belajar untuk merasa cukup dan puas dengan yang dimilikinya saat ini.
Bukan lebih banyak, tapi lebih bermakna
Hambatan terbesar untuk menikmati hidup dengan penuh berasal dari diri sendiri. Hambatan itu berupa pikiran irasional yang meyakini bahwa bila anda lambat, maka anda akan tertinggal dan terlindas. Bila anda tidak serakah, anda tidak akan kebagian. Bila anda mendapatkan lebih banyak, maka anda akan lebih bahagia. Pikiran-pikiran ini disebut irasional, karena sebenarnya tidak ada bukti yang kuat yang mendasarinya, namun kita toh meyakininya dengan membuta. Kalaupun kita menyadari bahwa pikiran itu keliru, seringkali kita tidak cukup kuat untuk melawannya. Kita telah terbiasa untuk mengikuti pikiran irasional tersebut, karena takut bila tidak mengikutinya maka suatu hal buruk akan menimpa kita.
Pikiran irasional mesti digantikan dengan pikiran rasional. Pikiran rasional berdasarkan pada bukti di kenyataan dan membantu kita menyesuaikan diri lebih baik. Seorang psikolog terkemuka bernama Mihaly Csikszentmihalyi telah melakukan penelitian pada orang-orang yang paling sukses dan paling kreatif di bidangnya masing-masing, misalnya: Atlet peraih emas Olimpiade, Ilmuwan peraih Nobel, Artis peraih Oscar. Penelitiannya menunjukkan bahwa faktor yang terpenting pada keberhasilan mereka bukanlah kerja sekeras mungkin untuk meraih sebanyak mungkin – sungguhpun mereka harus bekerja keras – melainkan kerja dengan suatu keasyikan untuk melakukan sesuatu yang bermakna. Mengerjakan sesuatu yang bermakna dengan penuh keasyikan disebut Csikszentmihalyi dengan istilah Flow. Orang-orang yang sungguh sukses, justru telah belajar bagaimana untuk meredakan dorongan hati yang serakah untuk meraih semuanya, melainkan fokus pada sedikit hal saja yang bermakna. They do less, so they can do better.
Oleh karena itu, marilah kita menjalani dan menikmati hidup kita, pekerjaan kita, relasi kita dengan keluarga dan teman dengan penuh keasyikan, dan rasa syukur. Waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali, maka nikmatilah saat ini sepenuhnya. Santai man…
Iman Setiadi Arif
Dekan Fakultas Psikologi Ukrida – Jakarta
Santai man...
Santai man…
Tulisan ini pernah dimuat di Harian Suara Pembaruan
Beberapa waktu yang lalu, diputar di bioskop-bioskop Jakarta, sebuah film komedi berjudul “Click!”. Tokoh utamanya diperankan oleh Adam Sandler. Sandler adalah seorang arsitek junior, yang tengah berjuang untuk meningkatkan karirnya di tengah persaingan yang sangat ketat dan tekanan kerja yang sangat berat. Seringkali ia harus mengorbankan waktunya untuk keluarga, agar dapat mengejar ambisinya untuk menjadi partner di dalam biro arsitek di tempatnya bekerja.
Dikisahkan bahwa Sandler kemudian diberi sebuah remote control ajaib, oleh seorang tokoh misterius yang diperankan oleh Christopher Walken. Tidak seperti remote control yang biasa, remote control ajaib ini dapat diarahkan pada sembarang benda, dan dapat mengendalikan benda tersebut, sebagaimana kita mengendalikan acara teve. Misalnya, Sandler dapat memperkecil volume suara gonggongan anjingnya yang berisik, dapat membuat boss-nya yang sedang mengomel berhenti, bahkan yang paling hebat adalah ia dapat memajukan (fast forwarding) waktu sekehendak hatinya. Bilamana ia sedang mengerjakan tugas yang membuatnya penat, ia dapat memajukan waktu sehingga tiba-tiba ia sudah berada di masa yang akan datang, di mana tugas tersebut telah selesai. Bilamana ia terjebak dalam kemacetan, ia pun tinggal memajukan waktu, sehingga tiba-tiba ia sudah berada di luar kemacetan.
Sandler merasa menjadi orang paling berbahagia di dunia dengan remote control ajaibnya ini; sampai ia mulai merasakan, bahwa lama kelamaan, bukan lagi dirinya yang mengendalikan remote control tersebut, melainkan remote control itu yang mengendalikan hidupnya. Remote control tersebut mulai bekerja secara otomatis, mengikuti pola kebiasaan Sandler selama ini. Ia selalu mempercepat waktu – tanpa diperintahkan lagi oleh Sandler – sehingga Sandler melewatkan bukan hanya hal-hal yang menyebalkannya, tetapi juga waktu-waktu yang paling bermakna dalam hidupnya. Tiba-tiba Sandler sudah menjadi partner senior di biro arsiteknya; tiba-tiba anak-anaknya sudah besar, tanpa Sandler dapat mengikuti perkembangannya dan menikmati perannya sebagai ayah bagi kedua anaknya; tiba-tiba ia sudah menjadi Arsitek yang super sukses, namun sekaligus sudah tua dan penyakitan, dan telah bercerai dengan istrinya. Sandler mencapai segala ambisinya – bahkan lebih dari itu – namun dengan pengorbanan yang mengerikan: ia tidak pernah dapat mengecap hidup yang dihabiskannya dengan begitu cepat.
Generasi yang diburu waktu
Film “Click!” adalah sebuah parodi tentang kehidupan di kota besar. Ia bicara tentang sebuah generasi yang diburu waktu. Semua orang di segala usia dituntut untuk melakukan lebih banyak hal, mencapai prestasi yang lebih baik lagi dan melakukan segala sesuatu dengan secepat mungkin. Para motivator terus menerus menanamkan ide di kepala kita, bahwa jangan pernah kita merasa puas, melainkan kita harus terus merasa haus untuk mendapatkan lebih banyak lagi dari hidup ini. Orang jadi merasa bersalah kalau ia tidak sibuk dan tergoda untuk bersantai sedikit saja. Sekarang kita sudah biasa melihat anak SD - atau bahkan TK - yang mendorong tasnya yang penuh sesak dengan buku, dari satu tempat kursus ke tempat kursus yang lain. Bilamana anak berusia 1 tahun baru dapat mengucapkan satu dua patah kata, orangtuanya sudah khawatir bahwa anaknya menderita autism dan segera membawa anaknya ke tempat speech therapy. Kursus untuk membaca dan menghitung cepat, laris manis diikuti orang-orang dari pelbagai usia. Singkat kata, seperti Adam Sandler di film “Click!” kita selalu memfast-forward hidup kita, sampai hidup itu habis tanpa kita sempat mengecapnya.
Kerinduan untuk mengecap kehidupan
Di lubuk hati orang-orang modern, tersimpan kerinduan untuk mengecap kehidupan. Mulai terbit kesadaran bahwa bekerja lebih keras dan memperoleh materi lebih banyak lagi, tidak dengan sendirinya membawa kebahagiaan. Namun, belenggu kebiasaan dan tekanan masyarakat yang sangat kuat kadang terlalu kuat untuk ditolak.
Berikut adalah beberapa teknik yang dikembangkan oleh psikologi modern untuk mematahkan belenggu dan tekanan itu dan mulai mengecap anugerah kehidupan yang diberikan kepada kita.
Savoring
Salah satu cara untuk berbahagia adalah dengan hidup di saat ini. Fred B. Bryant dan Joseph Veroff dari Loyola University adalah para psikolog yang mengembangkan konsep yang disebut Savoring. Savoring berarti kesadaran penuh akan kesenangan yang dialami saat ini, dan dengan sengaja memusatkan perhatian pada perasaan itu dan menikmatinya selagi berlangsung.
Mereka mengajar para siswanya untuk berlatih Savoring dengan cara meluangkan waktu untuk melakukan salah satu kegiatan yang disukai, dan memusatkan perhatian pada kegiatan itu saja. Misalnya: seorang siswa memilih untuk membaca puisi yang disukainya. Siswa itu dianjurkan untuk membaca kata demi kata dalam puisi tersebut dengan penuh perhatian, membiarkan kata-kata itu mengalir tanpa terburu-buru dan meresapi diri mereka perlahan-lahan. Saat orang melakukan Savoring, waktu berlalu tanpa terasa – namun setiap detik dihayati dengan penuh. Orang akan merasakan kelegaan dan kedamaian yang belum pernah dirasakannya, dan tidak jarang hatinya meluap dengan kebahagiaan. Orang belajar untuk merasa cukup dan puas dengan yang dimilikinya saat ini.
Bukan lebih banyak, tapi lebih bermakna
Hambatan terbesar untuk menikmati hidup dengan penuh berasal dari diri sendiri. Hambatan itu berupa pikiran irasional yang meyakini bahwa bila anda lambat, maka anda akan tertinggal dan terlindas. Bila anda tidak serakah, anda tidak akan kebagian. Bila anda mendapatkan lebih banyak, maka anda akan lebih bahagia. Pikiran-pikiran ini disebut irasional, karena sebenarnya tidak ada bukti yang kuat yang mendasarinya, namun kita toh meyakininya dengan membuta. Kalaupun kita menyadari bahwa pikiran itu keliru, seringkali kita tidak cukup kuat untuk melawannya. Kita telah terbiasa untuk mengikuti pikiran irasional tersebut, karena takut bila tidak mengikutinya maka suatu hal buruk akan menimpa kita.
Pikiran irasional mesti digantikan dengan pikiran rasional. Pikiran rasional berdasarkan pada bukti di kenyataan dan membantu kita menyesuaikan diri lebih baik. Seorang psikolog terkemuka bernama Mihaly Csikszentmihalyi telah melakukan penelitian pada orang-orang yang paling sukses dan paling kreatif di bidangnya masing-masing, misalnya: Atlet peraih emas Olimpiade, Ilmuwan peraih Nobel, Artis peraih Oscar. Penelitiannya menunjukkan bahwa faktor yang terpenting pada keberhasilan mereka bukanlah kerja sekeras mungkin untuk meraih sebanyak mungkin – sungguhpun mereka harus bekerja keras – melainkan kerja dengan suatu keasyikan untuk melakukan sesuatu yang bermakna. Mengerjakan sesuatu yang bermakna dengan penuh keasyikan disebut Csikszentmihalyi dengan istilah Flow. Orang-orang yang sungguh sukses, justru telah belajar bagaimana untuk meredakan dorongan hati yang serakah untuk meraih semuanya, melainkan fokus pada sedikit hal saja yang bermakna. They do less, so they can do better.
Oleh karena itu, marilah kita menjalani dan menikmati hidup kita, pekerjaan kita, relasi kita dengan keluarga dan teman dengan penuh keasyikan, dan rasa syukur. Waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali, maka nikmatilah saat ini sepenuhnya. Santai man…
Iman Setiadi Arif
Dekan Fakultas Psikologi Ukrida – Jakarta
Tulisan ini pernah dimuat di Harian Suara Pembaruan
Beberapa waktu yang lalu, diputar di bioskop-bioskop Jakarta, sebuah film komedi berjudul “Click!”. Tokoh utamanya diperankan oleh Adam Sandler. Sandler adalah seorang arsitek junior, yang tengah berjuang untuk meningkatkan karirnya di tengah persaingan yang sangat ketat dan tekanan kerja yang sangat berat. Seringkali ia harus mengorbankan waktunya untuk keluarga, agar dapat mengejar ambisinya untuk menjadi partner di dalam biro arsitek di tempatnya bekerja.
Dikisahkan bahwa Sandler kemudian diberi sebuah remote control ajaib, oleh seorang tokoh misterius yang diperankan oleh Christopher Walken. Tidak seperti remote control yang biasa, remote control ajaib ini dapat diarahkan pada sembarang benda, dan dapat mengendalikan benda tersebut, sebagaimana kita mengendalikan acara teve. Misalnya, Sandler dapat memperkecil volume suara gonggongan anjingnya yang berisik, dapat membuat boss-nya yang sedang mengomel berhenti, bahkan yang paling hebat adalah ia dapat memajukan (fast forwarding) waktu sekehendak hatinya. Bilamana ia sedang mengerjakan tugas yang membuatnya penat, ia dapat memajukan waktu sehingga tiba-tiba ia sudah berada di masa yang akan datang, di mana tugas tersebut telah selesai. Bilamana ia terjebak dalam kemacetan, ia pun tinggal memajukan waktu, sehingga tiba-tiba ia sudah berada di luar kemacetan.
Sandler merasa menjadi orang paling berbahagia di dunia dengan remote control ajaibnya ini; sampai ia mulai merasakan, bahwa lama kelamaan, bukan lagi dirinya yang mengendalikan remote control tersebut, melainkan remote control itu yang mengendalikan hidupnya. Remote control tersebut mulai bekerja secara otomatis, mengikuti pola kebiasaan Sandler selama ini. Ia selalu mempercepat waktu – tanpa diperintahkan lagi oleh Sandler – sehingga Sandler melewatkan bukan hanya hal-hal yang menyebalkannya, tetapi juga waktu-waktu yang paling bermakna dalam hidupnya. Tiba-tiba Sandler sudah menjadi partner senior di biro arsiteknya; tiba-tiba anak-anaknya sudah besar, tanpa Sandler dapat mengikuti perkembangannya dan menikmati perannya sebagai ayah bagi kedua anaknya; tiba-tiba ia sudah menjadi Arsitek yang super sukses, namun sekaligus sudah tua dan penyakitan, dan telah bercerai dengan istrinya. Sandler mencapai segala ambisinya – bahkan lebih dari itu – namun dengan pengorbanan yang mengerikan: ia tidak pernah dapat mengecap hidup yang dihabiskannya dengan begitu cepat.
Generasi yang diburu waktu
Film “Click!” adalah sebuah parodi tentang kehidupan di kota besar. Ia bicara tentang sebuah generasi yang diburu waktu. Semua orang di segala usia dituntut untuk melakukan lebih banyak hal, mencapai prestasi yang lebih baik lagi dan melakukan segala sesuatu dengan secepat mungkin. Para motivator terus menerus menanamkan ide di kepala kita, bahwa jangan pernah kita merasa puas, melainkan kita harus terus merasa haus untuk mendapatkan lebih banyak lagi dari hidup ini. Orang jadi merasa bersalah kalau ia tidak sibuk dan tergoda untuk bersantai sedikit saja. Sekarang kita sudah biasa melihat anak SD - atau bahkan TK - yang mendorong tasnya yang penuh sesak dengan buku, dari satu tempat kursus ke tempat kursus yang lain. Bilamana anak berusia 1 tahun baru dapat mengucapkan satu dua patah kata, orangtuanya sudah khawatir bahwa anaknya menderita autism dan segera membawa anaknya ke tempat speech therapy. Kursus untuk membaca dan menghitung cepat, laris manis diikuti orang-orang dari pelbagai usia. Singkat kata, seperti Adam Sandler di film “Click!” kita selalu memfast-forward hidup kita, sampai hidup itu habis tanpa kita sempat mengecapnya.
Kerinduan untuk mengecap kehidupan
Di lubuk hati orang-orang modern, tersimpan kerinduan untuk mengecap kehidupan. Mulai terbit kesadaran bahwa bekerja lebih keras dan memperoleh materi lebih banyak lagi, tidak dengan sendirinya membawa kebahagiaan. Namun, belenggu kebiasaan dan tekanan masyarakat yang sangat kuat kadang terlalu kuat untuk ditolak.
Berikut adalah beberapa teknik yang dikembangkan oleh psikologi modern untuk mematahkan belenggu dan tekanan itu dan mulai mengecap anugerah kehidupan yang diberikan kepada kita.
Savoring
Salah satu cara untuk berbahagia adalah dengan hidup di saat ini. Fred B. Bryant dan Joseph Veroff dari Loyola University adalah para psikolog yang mengembangkan konsep yang disebut Savoring. Savoring berarti kesadaran penuh akan kesenangan yang dialami saat ini, dan dengan sengaja memusatkan perhatian pada perasaan itu dan menikmatinya selagi berlangsung.
Mereka mengajar para siswanya untuk berlatih Savoring dengan cara meluangkan waktu untuk melakukan salah satu kegiatan yang disukai, dan memusatkan perhatian pada kegiatan itu saja. Misalnya: seorang siswa memilih untuk membaca puisi yang disukainya. Siswa itu dianjurkan untuk membaca kata demi kata dalam puisi tersebut dengan penuh perhatian, membiarkan kata-kata itu mengalir tanpa terburu-buru dan meresapi diri mereka perlahan-lahan. Saat orang melakukan Savoring, waktu berlalu tanpa terasa – namun setiap detik dihayati dengan penuh. Orang akan merasakan kelegaan dan kedamaian yang belum pernah dirasakannya, dan tidak jarang hatinya meluap dengan kebahagiaan. Orang belajar untuk merasa cukup dan puas dengan yang dimilikinya saat ini.
Bukan lebih banyak, tapi lebih bermakna
Hambatan terbesar untuk menikmati hidup dengan penuh berasal dari diri sendiri. Hambatan itu berupa pikiran irasional yang meyakini bahwa bila anda lambat, maka anda akan tertinggal dan terlindas. Bila anda tidak serakah, anda tidak akan kebagian. Bila anda mendapatkan lebih banyak, maka anda akan lebih bahagia. Pikiran-pikiran ini disebut irasional, karena sebenarnya tidak ada bukti yang kuat yang mendasarinya, namun kita toh meyakininya dengan membuta. Kalaupun kita menyadari bahwa pikiran itu keliru, seringkali kita tidak cukup kuat untuk melawannya. Kita telah terbiasa untuk mengikuti pikiran irasional tersebut, karena takut bila tidak mengikutinya maka suatu hal buruk akan menimpa kita.
Pikiran irasional mesti digantikan dengan pikiran rasional. Pikiran rasional berdasarkan pada bukti di kenyataan dan membantu kita menyesuaikan diri lebih baik. Seorang psikolog terkemuka bernama Mihaly Csikszentmihalyi telah melakukan penelitian pada orang-orang yang paling sukses dan paling kreatif di bidangnya masing-masing, misalnya: Atlet peraih emas Olimpiade, Ilmuwan peraih Nobel, Artis peraih Oscar. Penelitiannya menunjukkan bahwa faktor yang terpenting pada keberhasilan mereka bukanlah kerja sekeras mungkin untuk meraih sebanyak mungkin – sungguhpun mereka harus bekerja keras – melainkan kerja dengan suatu keasyikan untuk melakukan sesuatu yang bermakna. Mengerjakan sesuatu yang bermakna dengan penuh keasyikan disebut Csikszentmihalyi dengan istilah Flow. Orang-orang yang sungguh sukses, justru telah belajar bagaimana untuk meredakan dorongan hati yang serakah untuk meraih semuanya, melainkan fokus pada sedikit hal saja yang bermakna. They do less, so they can do better.
Oleh karena itu, marilah kita menjalani dan menikmati hidup kita, pekerjaan kita, relasi kita dengan keluarga dan teman dengan penuh keasyikan, dan rasa syukur. Waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali, maka nikmatilah saat ini sepenuhnya. Santai man…
Iman Setiadi Arif
Dekan Fakultas Psikologi Ukrida – Jakarta
Kebahagiaan atau Kesenangan
Kebahagiaan atau kesenangan?
Tulisan ini pernah dimuat di Harian Suara Pembaruan
Tujuan hidup manusia – entah ia seorang kaya atau miskin, pandai atau pandir, relijius atau ateis – adalah menuju kebahagiaan. Dalam hal ini, semua orang sama. (Tenzin Gyatso, Dalai Lama ke 14).
Beberapa waktu yang lalu, seorang ibu muda konseling dengan saya. Tampak jelas dari penampilannya, ia seorang yang berkecukupan. Ia mengemukakan bahwa ia memiliki seorang anak, namun ia sudah bercerai dengan suaminya 4 tahun yang lalu. Sekitar 2 tahun yang lalu, ia mulai menjalin relasi dengan seorang pria yang sudah beristri. Pria itu seorang yang baik, menyenangkan dan kaya raya. Sekitar 1 tahun yang lalu, ibu ini mulai memiliki kecurigaan bahwa kekasihnya itu berhubungan lagi dengan perempuan lain. Ia mulai merasa diasingkan. Ia merasa keluarganya tidak mendukungnya, dan orangtuanya membicarakannya di belakang. Ia curiga pula, bahwa kekasihnya mulai menjalin affair dengan kakaknya – yang juga seorang ibu muda yang sudah bercerai. Akhir-akhir ini kondisinya semakin buruk, ia mulai merasa teman-temannya menjauhinya dan berkomplot dengan kekasihnya untuk memata-matainya, orang-orang membicarakan dirinya, berita dan iklan di berbagai media massa menuding dirinya, bahkan ia tidak lagi menghadiri kebaktian di Gereja karena ia merasa pastor menyindir dirinya di dalam khotbah. Dalam penilaian saya sebagai seorang psikolog, ibu ini sedang menuju ke arah Paranoia.
Alarm Jiwa
Kecemasan, ketakutan dan berbagai gejala gangguan psikopatologi adalah bunyi alarm jiwa yang hendak menyerukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup seseorang. Ia hendak membangunkan seseorang yang terlelap dalam hidupnya, yang tidak mau menyadari bahwa api sudah menjilat kakinya. Bila seseorang mengabaikannya, maka suaranya akan makin keras, dan tanda-tanda gangguan akan makin nyata.
Gejala-gejala psikopatologi adalah seruan dari kedalaman jiwa seseorang, yang hendak menyatakan bahwa seseorang sedang bergerak menjauhi tujuan aslinya – yaitu kebahagiaan. Manusia diciptakan untuk berbahagia. Di dalam lubuk jiwanya yang terdalam telah tertanam kerinduan untuk berbahagia. Bila perjalanan hidupnya bergerak mendekati kebahagiaan, maka seluruh tanda-tanda kehidupannya – baik itu secara fisik, pikiran, emosi dan tingkah lakunya – akan mencerminkan kedamaian. Sebaliknya, bila perjalanan hidupnya bergerak menjauhi kebahagiaan, maka seluruh keberadaan dirinya akan dicekam oleh ketakutan dan kecemasan.
Kebahagiaan atau kesenangan?
Salah satu kekeliruan mendasar yang dialami banyak orang adalah menyamakan kebahagiaan (happiness) dengan kesenangan (pleasure). Banyak orang mengejar kesenangan dan menghindari penderitaan (Hedonist) – namun mereka tidak berbahagia. Sebaliknya, ada juga golongan tertentu yang dengan sangat keras menghindari kesenangan, bahkan kadang sengaja mencari penderitaan (Masochist) karena curiga bahwa setiap wujud kesenangan adalah dosa. Mereka juga tidak bahagia.
Sumber kesenangan adalah tercapainya keinginan – baik itu keinginan akan kenikmatan ragawi ataupun kenikmatan jiwa (misalnya: prestasi, popularitas, kekuasaan dll). Tidak ada yang salah dengan kesenangan, hanya saja kesenangan tidak akan pernah cukup. Tercapainya suatu keinginan – sebaik apapun keinginan tersebut – akan membuat seseorang semakin haus dan memiliki lebih banyak lagi keinginan.
Sumber kebahagiaan adalah bebasnya seseorang dari berbagai keinginan sehingga beroleh damai. Bila seseorang telah mengecap kebahagiaan, ia tidak akan lagi haus, melainkan kebahagiaan itu akan menjadi mata air di dalam hatinya yang terus menerus memancarkan kesegarannya.
Jalan sederhana menuju kebahagiaan
Orang bijaksana – yaitu orang yang sudah berbahagia – berkata bahwa Kebahagiaan sejati dan Kebenaran tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Kebahagiaan dan Kebenaran mesti dialami langsung. Memang, orang lebih senang berwacana tentang kemujaraban suatu obat, daripada meminumnya. Namun, wacana dan kata-kata tetap diperlukan – paling tidak untuk sementara – sebagai tangga untuk naik ke tempat yang dituju.
Perkenankanlah penulis bergerak di dunia wacana dan mengemukakan teori, karena psikolog akan gulung tikar bilamana ia sudah tidak boleh berkata-kata J. Seorang psikolog dari University of Pennsylvania, yaitu Martin Seligman, mengemukakan resep sederhana untuk bahagia. Menurut Seligman, cara untuk berbahagia adalah dengan menjalani hidup di mana terdapat 3 hal: 1)Emosi positif, 2)Keterikatan penuh dan sukarela (Engagement) kepada hidup yang dijalani dan 3)Makna hidup.
Emosi positif
Seorang yang bahagia akan lebih sering mengalami emosi positif tentang masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang, serta telah belajar untuk meningkatkan perasaan-perasaan positif ini. Emosi positif tentang masa lalu meliputi: kepuasan, kedamaian, kebanggaan (sebagai lawan dari penyesalan) rasa syukur, dll. Emosi positif tentang masa kini dan masa yang akan datang meliputi: harapan dan optimisme, keyakinan dan kepercayaan diri, dll.
Keterikatan penuh dan sukarela
Yaitu hidup yang dijalani dengan penuh, di mana terdapat keterlibatan dan komitmen sepenuhnya terhadap kerja, relasi intim dan rekreasi. Salah seorang rekan Seligman yang bernama Mihaly Csikszentmihalyi mengemukakan konsep yang dinamainya “Flow” yaitu keadaan psikologis di mana seseorang mengalami konsentrasi yang sepenuhnya – tanpa harus berusaha keras – karena begitu terserap dengan asyiknya pada aktivitas yang sedang dilakukannya. Dalam keadaan flow, kesadaran seseorang meningkat dan segala tindakannya dilakukan dengan mudah dan dengan hasil yang paling optimal.
Seligman mengatakan bahwa cara untuk menjalani hidup dengan keterikatan penuh dan sukarela adalah dengan menemukan bakat-bakat dan kekuatan-kekuatan asli orang tersebut (signature strengths) dan belajar untuk menggunakannya lebih sering. Banyak orang tercekam dan menyesali kekurangan-kekurangan dirinya, serta menghabiskan energi untuk menghilangkan atau menutupi kekurangan tersebut. Menurut Seligman, yang harus dilakukan adalah mengedepankan kekuatan yang dimiliki, dan biarkan kelemahan yang ada menjadi latar belakang.
Makna hidup
Yaitu menemukan tujuan utama dan panggilan terdalam yang dimiliki seseorang dalam kehidupannya. Sumber-sumber makna hidup dapat ditemukan dalam agama, keyakinan, kecintaan akan tanah air, dll. Tiap orang memiliki cara dan sumber yang unik dalam menemukan makna hidupnya. Makna hidup akan membuat seseorang mencurahkan segenap cinta, bakat, kemampuan dan hal yang dimiliki untuk menjadi bagian dan melayani hal yang lebih besar daripada Ego-nya.
Penulis bertanya kepada ibu muda yang diliputi ketakutan dalam wujud kecurigaan, apakah yang sebenarnya dicarinya dalam hidup ini? Ia menjawab, “Tentunya, kebahagiaan.” Penulis bertanya lagi, apakah relasi yang dijalinnya dengan pria beristri itu akan membawanya pada kebahagiaan? Ia menjawab,”Saya tahu bahwa sebenarnya hal itu tidak akan pernah membawa saya pada kebahagiaan yang saya cari.” Maka penulis berkata padanya,”Kalau anda menuju ke suatu tempat dengan menggunakan suatu bus – dan di tengah jalan anda sadar bahwa bus itu menuju tempat yang keliru, berhentilah segera. Pindahlah dari bus yang keliru ini, ke bus lain yang akan membawa anda kepada tempat yang dituju.” Para pembaca yang budiman, apakah “bus” yang anda tumpangi saat ini sudah menuju ke tempat yang anda tuju? Semoga kita semua berbahagia…
Iman Setiadi Arif
(Dekan dan Staff pengajar F.Psikologi Ukrida – Jakarta)
Tulisan ini pernah dimuat di Harian Suara Pembaruan
Tujuan hidup manusia – entah ia seorang kaya atau miskin, pandai atau pandir, relijius atau ateis – adalah menuju kebahagiaan. Dalam hal ini, semua orang sama. (Tenzin Gyatso, Dalai Lama ke 14).
Beberapa waktu yang lalu, seorang ibu muda konseling dengan saya. Tampak jelas dari penampilannya, ia seorang yang berkecukupan. Ia mengemukakan bahwa ia memiliki seorang anak, namun ia sudah bercerai dengan suaminya 4 tahun yang lalu. Sekitar 2 tahun yang lalu, ia mulai menjalin relasi dengan seorang pria yang sudah beristri. Pria itu seorang yang baik, menyenangkan dan kaya raya. Sekitar 1 tahun yang lalu, ibu ini mulai memiliki kecurigaan bahwa kekasihnya itu berhubungan lagi dengan perempuan lain. Ia mulai merasa diasingkan. Ia merasa keluarganya tidak mendukungnya, dan orangtuanya membicarakannya di belakang. Ia curiga pula, bahwa kekasihnya mulai menjalin affair dengan kakaknya – yang juga seorang ibu muda yang sudah bercerai. Akhir-akhir ini kondisinya semakin buruk, ia mulai merasa teman-temannya menjauhinya dan berkomplot dengan kekasihnya untuk memata-matainya, orang-orang membicarakan dirinya, berita dan iklan di berbagai media massa menuding dirinya, bahkan ia tidak lagi menghadiri kebaktian di Gereja karena ia merasa pastor menyindir dirinya di dalam khotbah. Dalam penilaian saya sebagai seorang psikolog, ibu ini sedang menuju ke arah Paranoia.
Alarm Jiwa
Kecemasan, ketakutan dan berbagai gejala gangguan psikopatologi adalah bunyi alarm jiwa yang hendak menyerukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup seseorang. Ia hendak membangunkan seseorang yang terlelap dalam hidupnya, yang tidak mau menyadari bahwa api sudah menjilat kakinya. Bila seseorang mengabaikannya, maka suaranya akan makin keras, dan tanda-tanda gangguan akan makin nyata.
Gejala-gejala psikopatologi adalah seruan dari kedalaman jiwa seseorang, yang hendak menyatakan bahwa seseorang sedang bergerak menjauhi tujuan aslinya – yaitu kebahagiaan. Manusia diciptakan untuk berbahagia. Di dalam lubuk jiwanya yang terdalam telah tertanam kerinduan untuk berbahagia. Bila perjalanan hidupnya bergerak mendekati kebahagiaan, maka seluruh tanda-tanda kehidupannya – baik itu secara fisik, pikiran, emosi dan tingkah lakunya – akan mencerminkan kedamaian. Sebaliknya, bila perjalanan hidupnya bergerak menjauhi kebahagiaan, maka seluruh keberadaan dirinya akan dicekam oleh ketakutan dan kecemasan.
Kebahagiaan atau kesenangan?
Salah satu kekeliruan mendasar yang dialami banyak orang adalah menyamakan kebahagiaan (happiness) dengan kesenangan (pleasure). Banyak orang mengejar kesenangan dan menghindari penderitaan (Hedonist) – namun mereka tidak berbahagia. Sebaliknya, ada juga golongan tertentu yang dengan sangat keras menghindari kesenangan, bahkan kadang sengaja mencari penderitaan (Masochist) karena curiga bahwa setiap wujud kesenangan adalah dosa. Mereka juga tidak bahagia.
Sumber kesenangan adalah tercapainya keinginan – baik itu keinginan akan kenikmatan ragawi ataupun kenikmatan jiwa (misalnya: prestasi, popularitas, kekuasaan dll). Tidak ada yang salah dengan kesenangan, hanya saja kesenangan tidak akan pernah cukup. Tercapainya suatu keinginan – sebaik apapun keinginan tersebut – akan membuat seseorang semakin haus dan memiliki lebih banyak lagi keinginan.
Sumber kebahagiaan adalah bebasnya seseorang dari berbagai keinginan sehingga beroleh damai. Bila seseorang telah mengecap kebahagiaan, ia tidak akan lagi haus, melainkan kebahagiaan itu akan menjadi mata air di dalam hatinya yang terus menerus memancarkan kesegarannya.
Jalan sederhana menuju kebahagiaan
Orang bijaksana – yaitu orang yang sudah berbahagia – berkata bahwa Kebahagiaan sejati dan Kebenaran tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Kebahagiaan dan Kebenaran mesti dialami langsung. Memang, orang lebih senang berwacana tentang kemujaraban suatu obat, daripada meminumnya. Namun, wacana dan kata-kata tetap diperlukan – paling tidak untuk sementara – sebagai tangga untuk naik ke tempat yang dituju.
Perkenankanlah penulis bergerak di dunia wacana dan mengemukakan teori, karena psikolog akan gulung tikar bilamana ia sudah tidak boleh berkata-kata J. Seorang psikolog dari University of Pennsylvania, yaitu Martin Seligman, mengemukakan resep sederhana untuk bahagia. Menurut Seligman, cara untuk berbahagia adalah dengan menjalani hidup di mana terdapat 3 hal: 1)Emosi positif, 2)Keterikatan penuh dan sukarela (Engagement) kepada hidup yang dijalani dan 3)Makna hidup.
Emosi positif
Seorang yang bahagia akan lebih sering mengalami emosi positif tentang masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang, serta telah belajar untuk meningkatkan perasaan-perasaan positif ini. Emosi positif tentang masa lalu meliputi: kepuasan, kedamaian, kebanggaan (sebagai lawan dari penyesalan) rasa syukur, dll. Emosi positif tentang masa kini dan masa yang akan datang meliputi: harapan dan optimisme, keyakinan dan kepercayaan diri, dll.
Keterikatan penuh dan sukarela
Yaitu hidup yang dijalani dengan penuh, di mana terdapat keterlibatan dan komitmen sepenuhnya terhadap kerja, relasi intim dan rekreasi. Salah seorang rekan Seligman yang bernama Mihaly Csikszentmihalyi mengemukakan konsep yang dinamainya “Flow” yaitu keadaan psikologis di mana seseorang mengalami konsentrasi yang sepenuhnya – tanpa harus berusaha keras – karena begitu terserap dengan asyiknya pada aktivitas yang sedang dilakukannya. Dalam keadaan flow, kesadaran seseorang meningkat dan segala tindakannya dilakukan dengan mudah dan dengan hasil yang paling optimal.
Seligman mengatakan bahwa cara untuk menjalani hidup dengan keterikatan penuh dan sukarela adalah dengan menemukan bakat-bakat dan kekuatan-kekuatan asli orang tersebut (signature strengths) dan belajar untuk menggunakannya lebih sering. Banyak orang tercekam dan menyesali kekurangan-kekurangan dirinya, serta menghabiskan energi untuk menghilangkan atau menutupi kekurangan tersebut. Menurut Seligman, yang harus dilakukan adalah mengedepankan kekuatan yang dimiliki, dan biarkan kelemahan yang ada menjadi latar belakang.
Makna hidup
Yaitu menemukan tujuan utama dan panggilan terdalam yang dimiliki seseorang dalam kehidupannya. Sumber-sumber makna hidup dapat ditemukan dalam agama, keyakinan, kecintaan akan tanah air, dll. Tiap orang memiliki cara dan sumber yang unik dalam menemukan makna hidupnya. Makna hidup akan membuat seseorang mencurahkan segenap cinta, bakat, kemampuan dan hal yang dimiliki untuk menjadi bagian dan melayani hal yang lebih besar daripada Ego-nya.
Penulis bertanya kepada ibu muda yang diliputi ketakutan dalam wujud kecurigaan, apakah yang sebenarnya dicarinya dalam hidup ini? Ia menjawab, “Tentunya, kebahagiaan.” Penulis bertanya lagi, apakah relasi yang dijalinnya dengan pria beristri itu akan membawanya pada kebahagiaan? Ia menjawab,”Saya tahu bahwa sebenarnya hal itu tidak akan pernah membawa saya pada kebahagiaan yang saya cari.” Maka penulis berkata padanya,”Kalau anda menuju ke suatu tempat dengan menggunakan suatu bus – dan di tengah jalan anda sadar bahwa bus itu menuju tempat yang keliru, berhentilah segera. Pindahlah dari bus yang keliru ini, ke bus lain yang akan membawa anda kepada tempat yang dituju.” Para pembaca yang budiman, apakah “bus” yang anda tumpangi saat ini sudah menuju ke tempat yang anda tuju? Semoga kita semua berbahagia…
Iman Setiadi Arif
(Dekan dan Staff pengajar F.Psikologi Ukrida – Jakarta)
Langganan:
Postingan (Atom)

.jpg)