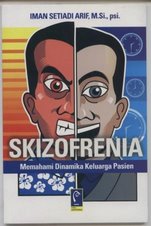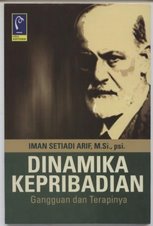Bilamana kita mendengar istilah “luka batin” maka konotasi kita langsung terarah pada seseorang yang mengalami trauma psikologis akibat perlakuan orangtua kepadanya di masa kecil. Dalam uraian semacam itu biasanya akan dibahas bagaimana seseorang yang di masa kecilnya kurang mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perlakuan kasar atau penolakan dari orangtua akan mengalami trauma (luka batin) yang kemudian membangkitkan konflik berkepanjangan dalam dirinya. Kondisi ini akan berujung pada munculnya berbagai gejala gangguan psikologis dan gangguan dalam relasi dengan orang lain. Biasanya dalam kasus-kasus semacam ini orangtua akan ditempatkan sebagai the aggressor (pihak yang menyerang), sementara anak akan dipandang sebagai the victim (pihak yang menjadi korban). Dalam pandangan semacam ini, masalah terlalu disederhanakan dan dipandang secara hitam-putih. Jarang sekali ada pembahasan pada arah sebaliknya, yaitu orangtua yang mengalami luka batin di dalam interaksi dengan anaknya. Sementara pada kenyataannya, di dalam tiap relasi selalu terdapat kemungkinan yang sama besarnya bagi kedua pihak untuk saling melukai satu sama lain.
Pada tahun 60’an ada seorang tokoh psikiatri yang sangat terkenal karena kejeniusan dan juga sikap ekstrimnya; namanya adalah R.D. Laing. Di usia belia (awal 30-an tahun) ia sudah menerbitkan sebuah buku yang mendapatkan sambutan sangat hangat dan kemudian memiliki pengaruh besar di dunia psikiatri tahun 60an. Buku itu berjudul “The Divided Self”, yang pada intinya berisi analisis Laing tentang relasi pasien-pasien skizofrenia dengan orangtuanya. Untuk informasi bagi pembaca, skizofrenia adalah gangguan jiwa yang sangat berat, di mana pasien kehilangan kontak dengan realitas dan menunjukkan perilaku yang sangat terganggu, misalnya halusinasi – mendengar atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada – ataupun waham – di mana ia memiliki keyakinan yang ganjil dan tidak nyata, namun sangat diyakininya. Dalam bahasa sehari-hari, penderita skizofrenia biasa disebut “gila”.
Dengan analisis eksistensial yang mendalam dan meyakinkan, Laing menggambarkan bahwa skizofrenia yang dialami pasien merupakan respon normal yang ditunjukkannya karena keberadaannya dinafikan oleh orangtuanya. Orangtua secara tidak sadar meniadakan atau bahkan menyerang keberadaan pasien. Penolakan dari orangtua membuat pasien menolak dirinya sendiri. Akibatnya kepribadian pasien mengalami keterpecahan dan ia tidak dapat mengalami kebersamaan dengan orang lain. Secara eksistensial ia merasa terasing dari dunia ini dan karenanya semakin menjauh dari realitas; sehingga pada akhirnya mengalami kegilaan.
Teori Laing mendapat sambutan luas dan mempengaruhi pandangan arus utama saat itu. Orangtua dianggap berperan besar dalam mengakibatkan salah satu anggotanya menjadi gila; oleh karena itu orangtua harus diterapi dan diubah agar anak mereka sembuh. Dalam tinjauan balik tentang teori Laing di masa kini, pada ahli pada umumnya berpendapat bahwa teori Laing tidak sepenuhnya salah; setidaknya untuk beberapa kasus, memang ada dinamika keluarga patologis yang berperanan pada munculnya skizofrenia dalam diri anak. Namun teori Laing kemudian sangat dikecam karena ia hanya mengisahkan setengah dari cerita yang ada. Ia menutup mata pada setengah cerita yang lain, di mana sebagian orangtua sangat dilukai oleh perilaku putera-puteri mereka yang sangat mereka kasihi.
Kisah ibu Dora
Bu Dora (bukan nama sesungguhnya) adalah ibu dari seorang pasien skizofrenia yang bernama Roby (bukan nama sesungguhnya). Dari pernikahannya, Dora dikaruniai tujuh orang anak, di mana Roby adalah anak keempat. Roby memiliki waham bahwa ia adalah titisan sang mesias, dan ia memaksa seluruh anggota keluarga lain untuk mengakui hal tersebut. Tidak jarang saat Roby dikuasai waham, ia melakukan terror dan kekerasan pada orangtuanya, terutama pada Dora sebagai ibunya. Selain menghadapi terror fisik dan verbal, Dora juga harus berjuang hampir seorang diri dalam upaya menyembuhkan Roby, karena suami dan anak-anak lain kurang sekali mendukungnya. Malang nasib Dora, karena bukan cuma Roby yang sedang menderita penyakit yang menterrornya, melainkan juga anak-anak yang lain. Karena sikap Dora yang tegas, termasuk dalam hal penggunaan uang, anak-anak memusuhi dan mengucilkan Dora, menganggapnya tidak mencintai mereka dan hendak menguasai sendiri harta ayah mereka. Salah seorang anak Dora bahkan pernah menjambak dan mencekik Dora, serta mengancam hendak membakar dirinya bilamana tidak mengabulkan keinginannya.
Dalam analisis tentang riwayat penyakit Roby, tidak ditemui data yang kuat yang menunjukkan bahwa Roby menjadi sakit skizofrenia karena Dora. Sebaliknya kita melihat bahwa Dora seringkali dilukai oleh Roby (sekalipun tanpa disadarinya karena ia sedang dikuasai penyakitnya) dan juga oleh anak-anak lainnya. Dora hanyalah salah satu dari sekian banyak kasus, di mana orangtua bukan menjadi penyebab gangguan kejiwaan yang dialami anak mereka, melainkan menjadi pihak yang paling terbebani dan terluka oleh perilaku anak-anak mereka.
Kita dapat melihat beban serupa pada orangtua yang memiliki anak pecandu narkoba, anak yang mengidap HIV-AIDS, anak yang hamil di luar nikah, dan banyak kasus lain. Kita pun dapat mendengar kisah yang serupa pada para orangtua yang “dibuang” anak mereka ke panti jompo, ataupun orangtua yang mengalami kekerasan baik secara verbal ataupun fisik oleh anak-anak mereka sendiri.
Beban berganda
Bilamana seorang anak mengalami luka batin oleh orangtuanya, memang potensi trauma psikologis menjadi lebih besar daripada bila kejadiannya sebaliknya, yaitu orangtua yang terluka batin oleh anaknya. Kerentanan anak-anak yang lebih besar dikarenakan mereka masih sedang dalam proses pembentukan kepribadian, sedangkan orangtua diasumsikan sudah memiliki kepribadian yang kokoh sehingga lebih mampu mengelola luka batin yang dialami. Namun di sisi lain, anak akan terus bertumbuh dan dalam proses perkembangannya, ia akan bergerak memisahkan diri dari orangtua dan menjalin relasi-relasi intim dengan orang lain. Dalam relasi yang baru, seorang anak berpeluang menyembuhkan luka batin yang pernah dialaminya. Namun, bilamana yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu orangtua yang terluka batin oleh anaknya, maka menjadi lebih sulit untuk menyembuhkannya. Karena bagi orangtua, anak adalah orang yang terkasih yang tak tergantikan. Perjalanan orangtua bukanlah gerakan memisahkan diri dari anak, melainkan justru kebalikannya, yaitu sejalan usia biasanya orangtua semakin mendambakan kehadiran anak yang biasanya semakin menjauh karena sibuk dengan kehidupannya sendiri. Orang pun sering melupakan bahwa orangtua juga mungkin sekali memiliki luka batinnya sendiri di masa lalu oleh orangtua mereka. Dan relasi yang buruk dengan anak-anak mereka di masa kini, seringkali akan menguak kembali luka lama yang masih tersisa.
Di dalam kasus-kasus semacam bu Dora, seringkali orangtua mengalami beban berganda. Bukan cuma mereka harus terluka karena perlakuan anak-anak mereka; mereka juga harus berjuang dan mengorbankan waktu, tenaga, emosi dan juga sumberdaya finansial untuk menyediakan pengobatan dan pertolongan bagi anak mereka. Orangtua seringkali pula terkena stigma dari masyarakat yang mempersalahkan mereka atas perilaku anak-anak mereka. Masih sangat sedikit dukungan yang tersedia bagi para orangtua ini. Kebanyakan dari mereka seringkali harus menanggung beban berganda ini seorang diri, dan menderita dalam kebisuan.
Pentingnya kelompok pendukung
Sekarang semakin disadari pentingnya memberikan ruang bagi para orangtua yang memiliki putera-puteri dengan gangguan jiwa berat, untuk didengarkan curahan hati mereka dan diteguhkan kembali. Penting pula bagi keluarga untuk mendapatkan informasi-informasi yang lengkap tentang gangguan jiwa yang dialami putera-puteri mereka. Untuk itu, kehadiran kelompok pendukung (self-help group) akan sangat bermanfaat. Kelompok pendukung yang saya maksud, yang biasanya disusun secara swadaya, terdiri atas sesama orangtua yang memiliki permasalahan yang hampir serupa. Para profesional seperti psikiater, psikolog atau social worker, dapat menjadi fasilitator di dalam kelompok-kelompok semacam itu, terutama untuk memberikan edukasi yang sangat mereka butuhkan tentang permasalahan yang dihadapi anak mereka.
Sekarang sudah semakin banyak kelompok-kelompok semacam itu; misalnya kelompok orangtua anak autis, kelompok orangtua penderita skizofrenia, kelompok orangtua pecandu narkoba, dll. Dan data menunjukkan bahwa saat orangtua tidak lagi diposisikan sebagai penyebab masalah, melainkan sebagai pendukung utama pemulihan anak-anak mereka, maka baik sang pasien maupun keluarganya menjadi lebih sejahtera dan lebih dapat menyesuaikan diri. Kiranya dukungan dan kepedulian yang lebih besar pada keluarga-keluarga yang memiliki beban berat ini, perlu lebih ditingkatkan.
Iman Setiadi Arif, M.Si., Psi
Dekan Fakultas Psikologi UKRIDA – Jakarta

.jpg)