Tulisan ini pernah dimuat di Suara Pembaruan
Terselubungi oleh gegap gempita Pemilu Legislatif yang baru saja berlalu 9 April yang lalu, hari Minggu yang lalu tanggal 12 April 2009 bagi umat Kristiani adalah hari yang terpenting dan paling bermakna sepanjang tahun, yaitu hari raya Paskah. Kebangkitan Yesus Kristus (Isa Almasih) yang dihayati kembali (relived dalam kekinian - bukan sekedar “diperingati/ remembered” sebagai suatu peristiwa di masa lalu) setiap hari raya Paskah merupakan dasar iman dan pengharapan Kristiani.
Makna hidup seorang Kristen (Protestant dan Katolik) terletak pada iman dan pengharapan ini, bahwa kematian dan ketiadaan dikalahkan, dan hidup kekal dengan segala kepenuhannya dapat diperoleh dalam persekutuan dengan Kristus. Dalam sejarahnya yang panjang, terbukti bahwa iman dan pengharapan ini memampukan orang-orang Kristen menghadapi tantangan, kesulitan dan penindasan apapun sesuai dengan gerak zaman.
Semua agama merupakan sumber makna bagi para penganutnya. Dengan makna tersebut, seseorang dapat menjalani hidupnya dengan mantap, apapun yang terjadi dalam hidupnya tersebut. Saya mengutip dari Nietzsche yang mengatakan bahwa “Anyone who know the ‘why’ can bear any ‘how’.” Dalam hal ini bangsa
Karat materialisme yang menggerogoti
Di masyarakat Barat yang sangat ilmiah dan rasional, terjadi krisis spiritualitas yang parah – setidaknya sebagaimana tercermin dalam wacana-wacana mainstream yang berkembang di berbagai publikasi Ilmiah dan berbagai media. Semakin sulit tampaknya bagi masyarakat Barat yang modern dan postmodern ini untuk mempercayai sesuatu yang tak tampak dan tak dapat dibuktikan.
Kemajuan yang begitu pesat dalam dunia ilmu – disadari ataupun tidak – telah menjadikan sains sebagai pegangan satu-satunya dan sumber kebenaran tertinggi. Bila sesuatu dapat dibuktikan secara scientific, maka sesuatu itu nyata dan ada; sebaliknya bila tidak, maka ia tidak nyata dan tidak ada. Dan sayang sekali bahwa pengertian scientific telah disempitkan dan diidentikkan dengan materialisme. Dalam pandangan materialisme, yang sungguh-sungguh nyata dan ada adalah materi – yaitu apa yang bisa dilihat, diraba, dicium, dikecap, didengar, terikat pada ruang dan waktu. Apapun yang bukan materi, dianggap hanyalah ilusi atau bersifat sekunder sebagai akibat dari berbagai aktivitas materi.
Contoh yang paling jelas tentang hal ini tampak pada perkembangan mutakhir dalam neuroscience yang berparadigma materialistic (tidak semua neuroscience dan neuroscientist berparadigma seperti ini). Neuroscience merambah ke berbagai bidang seperti behavioral science, cognitive science, affective science, anthropology, philosophy dan bahkan akhir-akhir ini Theology. Neuroscience adalah bidang ilmu yang kajiannya adalah the brain, sementara berbagai ilmu lain yang saya sebut setelahnya bidang kajiannya adalah the mind. Yang dimaksud dengan the mind adalah segala inner experience sebagaimana secara dialami secara subjektif oleh individu, menggunakan sudut pandang orang pertama (1st person perspective); misalnya: perasaan, pikiran, keyakinan ataupun kehendak bebas individu. Sedangkan the brain adalah materi, yaitu organ biologis berupa otak dan seluruh sistem sarafnya, yang dapat diamati dan diperiksa secara objektif, menggunakan sudut pandang orang ketiga (3rd person perspective). Sekalipun jelas sekali bahwa ada hubungan erat antara the mind dan the brain, namun keduanya tak dapat diidentikkan. Masalahnya adalah materialisme mengidentikkan keduanya, dan mengatakan bahwa yang sungguh-sungguh real dan exist adalah the brain. The mind (pikiran, perasaan, kehendak, keyakinan, dll) hanyalah produk dari aktivitas the brain, sehingga mereka hanyalah ilusi, tidak sungguh-sungguh nyata dan ada.
Termasuk yang dinihilkan oleh pandangan sempit materialisme ini adalah berbagai pengalaman spiritual yang merupakan sumber makna bagi seseorang sebagai seorang pribadi ataupun suatu kelompok secara kolektif. Pengalaman-pengalaman spiritual (RSME = Religious, Spiritual, Mystical Experience) yang secara historis telah terbukti menjadi fondasi dan benteng terakhir individu dalam menghadapi deru kehidupan ini telah dinafikan dengan berbagai cara, dan orang-orang yang memperoleh pengalaman tersebut dilecehkan sebagai orang-orang yang mengalami semacam epilepsy, tumor otak, atau bahkan gangguan jiwa. Sebaik-baiknya, materialistic neuroscience hanya memandang spiritualitas sebagai semacam penyimpangan otak dan gangguan kejiwaan yang “diperlukan” demi survive-nya umat manusia.
Kalangan penganut agama dan spiritualitas tentu saja memberikan argumen perlawanan atas klaim-klaim kaum materialist. Namun, argumen-argumen mereka yang lebih sering didasarkan pada dogma dan falsafah serta kurang memiliki data-data ilmiah sebagai pendukungnya, jadi tampak lemah dan tertelan oleh argumentasi kaum materialist yang mengklaim memiliki bukti-bukti ilmiah sebagai dasar pandangan mereka.
Titik-titik cahaya di kegelapan
Tidak semua scientist berparadigma materialistic. Bahkan di dunia Fisika yang dianggap paling eksak sekalipun, kalangan arus utamanya tidak lagi berparadigma materialistic, terutama setelah ditemukannya Fisika Quantum dan asas ketidakpastian Heisenberg. Sekalipun tergolong pada kalangan minoritas, terdapat banyak neuroscientist yang berparadigma non-materialistic, dan penelitian-penelitian mereka mulai menjadi dasar argumentasi yang kuat bahwa hal-hal yang non-materi tidak dapat direduksi menjadi sekedar materi.
Andrew Newberg, M.D. dari
Penelitian yang lebih ekstensif dilakukan oleh Mario Beauregard, Ph.D. dari université de
Penelitian-penelitian Newberg dan Beauregard di atas adalah titik-titik cahaya di tengah dominasi materialisme yang menjadi arus utama saat ini. Suatu oase yang menyegarkan yang menegaskan bahwa pengalaman-pengalaman spiritual adalah sungguh nyata dan memiliki efek tranformatif dalam pribadi yang mengalaminya. Ditegaskan pula bahwa kehidupan seseorang tidak tergantung pada warisan genetic dan susunan syaraf yang dimilikinya, melainkan juga pada kehendak bebas dan pendisiplinan diri untuk berpaling pada Sumber yang lebih besar dari pribadinya sendiri, yaitu Sang Pencipta itu sendiri.
Iman Setiadi Arif
Dekan Fakultas Psikologi UKRIDA –

.jpg)
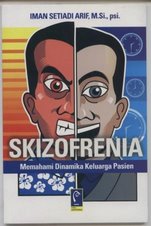
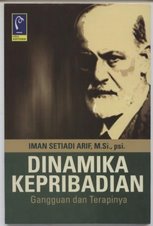



Tidak ada komentar:
Posting Komentar