Tulisan ini pernah dimuat di Suara Pembaruan
Di penghujung tahun 2009 ini bukan hanya cuaca Jakarta yang tak menentu, kadang begitu panas menyengat, disusul dengan hujan lebat dan banjir; seolah mengisyaratkan petaka dan membenarkan keyakinan sebagian orang akan datangnya kiamat di tahun 2012. Senada dengan bergolaknya alam, cuaca batin kita pun tengah diombang-ambingkan berbagai ketidakpastian, kekhawatiran dan ketakutan. Gonjang ganjing jagad eksternal yang tengah menaungi bangsa Indonesia – terutama kasus mafia peradilan dan bank Century – seperti menambah rentetan masalah yang menggayuti bangsa ini, bagaikan awal tebal yang menghalangi terbitnya cahaya pengharapan yang begitu dinantikan. Para elite menghirup bau busuk yang terkuak dan menjadi bangkit seleranya akan darah, dan tanpa memandang kotoran yang melekat di wajah sendiri, menjadikan situasi ini suatu kesempatan untuk membinasakan lawan yang dibenci. Rakyat jelata yang terlalu lama memikul beban berat, kian oleng dan tersengal-sengal menyaksikan permainan libidinal yang dipertontonkan dengan telanjang di hadapan mereka.
Seperti byar-pet nya listrik PLN, asa tiap insan di bumi Nusantara ini tengah meredup. Atmosphere kelabu yang membayangi seolah menindih berat-berat jagad batin kita, yang masih trauma setelah tertimpa berbagai bencana dan krisis. Memanasnya kawah Chandra Dimuka politik, sosial dan ekonomi, telah menanduskan pula hati kita. Kita menjadi apatis, pesimis dan sinis. Dalam kondisi ini, kita tergoda untuk menjadi bengis dan pemangsa sesama dengan moto SDM (Selamatkan diri masing-masing). Kerak di mata batin kita menebal dan kita mencari berbagai candu yang dapat melipur sedikit lara dan membawa kita pada sorga yang maya. Kita jadi gemar akan hantu-hantu dan teriakan histeris di televisi. Kita mau lari melupakan kenyataan pahit di dunia nyata dan mengubur diri dengan berbagai hiburan semu.
Nun jauh di lubuk hati kita, tersisa rindu. Rindu yang menyakitkan karena begitu lama tak tergugu. Rindu yang coba kita matikan, karena menjadi pengganggu kebahagiaan semu yang ingin kita aku. Rindu yang kita cemooh sebagai fantasi infantil dan tahyul masa lalu. Namun rindu itu pula yang menyisakan denyut di hati kita dan menghalanginya membatu. Rindu yang saya maksud adalah rindu akan datangnya pembaruan, yang menjadikan langit, bumi dan hati manusia yang baru. Rindu akan cahaya yang bersinar di kalbu, mengusir segala kegelapannya. Rindu akan air hidup yang memuaskan dahaga jiwa. Karena lubuk hati kita tahu, bahwa solusi akhir atas segala permasalahan di muka bumi ini bukanlah melalui revolusi. Penguasa yang tiran dapat digulingkan dan digantikan oleh penguasa baru, yang kelak menjadi tiran pula. Kemiskinan dapat dihilangkan di suatu belahan bumi, hanya untuk memindahkannya ke belahan bumi yang lain. Suatu penyakit dapat disembuhkan untuk digantikan dengan penyakit lain yang kelak membawa kita ke peti mati. Kerinduan dalam hati kita bukanlah pada solusi sementara yang menambal compang camping kemanusiaan kita dengan mengambil sobekan kain dari baju rombeng yang sama. Karena tidak ada yang sungguh baru di muka bumi ini dan segala sesuatu adalah sia-sia, sehingga hati kita jadi kelu. Kerinduan di hati kita adalah untuk kembali menjadi diri kita yang sejati sebagaimana tujuan asli kita diciptakan; dan hati kita tak mau yang kurang daripada itu. Di lubuk hati kita tahu bahwa kebahagiaan dan pembebasan merupakan harga mati dan hak waris sah kita yang sejati. Sampai hari itu tiba, kita semua mengerang kesakitan bagaikan perempuan yang hendak bersalin; dan kita menunggu untuk dilahirkan kembali.
Dan simbol apakah kiranya yang lebih baik untuk menggambarkan tanda akan datangnya pembaruan yang kita nantikan itu daripada simbol kelahiran seorang anak. Mata batin kita mengenal suatu tanda, suatu simbol yang menandakan datangnya pembaruan itu. Lahirnya seorang anak membawa hidup baru ke dunia ini, dan setiap kelahiran berarti harapan dan keberlangsungan hidup itu sendiri. Semua orangtua terhibur melihat lahirnya putera-puteri mereka, karena mereka tahu, sekalipun mereka akan mati, tetapi hidup berlangsung terus, dan keberadaan mereka terpelihara dalam diri keturunan mereka. Anak juga merupakan simbol kesucian, seperti metaphor yang kita lihat di cerita Peter Pan: Orang dewasa yang telah dikotori oleh banyak kekhawatiran, ketakutan, kebencian dan sakit hati sudah tidak dapat lagi melihat bidadari dan lupa cara untuk terbang masuk Neverland; hanya anak yang hatinya masih murni yang mampu. Karena hanya seorang yang menjadi anak dalam batinnya, yang dapat melihat tanah air sorgawi.
Hari Minggu ini umat Kristiani mulai memasuki masa Advent, yaitu menantikan kelahiran kanak-kanak Yesus. Yang kita rindukan, yang tak tergapai oleh segala usaha tapa brata dan berbagai laku penyucian diri, kini datang sendiri secara pribadi, hendak memberi diri bagi hati yang sungguh merindu. Sesuatu yang indah dan begitu lembut bersahaja sedang datang kepada kita. Sedemikian lembut, tanpa perbantahan, teriakan ataupun drama, sehingga begitu mudah luput dari perhatian kita. Tidak mudah untuk menyambut kehadirannya di hati, karena hati mesti hening dan bening untuk dapat mengenalnya. Di tengah kosmetika dan komersialisasi Natal yang begitu gencar mengepung kita, tidak mudah memelihara rasa rindu, agar tidak berpaling pada pemuasan semu yang merayu. Hati mesti kembali menjadi rumah doa dan segala kericuhan para pedagang dan penukar uang, mesti diusir pergi. Baru dengan demikian bintang Timur dapat terlihat lagi, dan menunjukkan bahwa kekasih yang dinanti sudah selalu berdiri di depan pintu dan mengetuk, dan segala dahaga dan rindu di hati akan terpuaskan. Selamat memasuki masa Advent, semoga bertemu dengan kekasih yang dirindu.
IMAN SETIADI ARIF
DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA – JAKARTA
Senin, 22 Februari 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

.jpg)
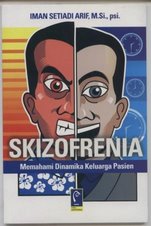
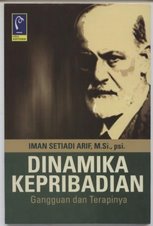



Tidak ada komentar:
Posting Komentar