Pengecut…
Tulisan ini pernah dimuat di Harian Suara Pembaruan
Beberapa waktu yang lalu, penulis menghadiri misa Requiem salah seorang jemaat Gereja penulis, yang menjadi korban dalam kecelakaan pesawat Garuda di Jogjakarta. Misa tersebut dilaksanakan dengan sangat indah dan mengharukan, sehingga kebanyakan peserta meneteskan air mata dalam keharuan bersama. Setelah perwakilan keluarga menyampaikan ucapan terakhir yang sangat menyentuh tentang almarhumah, giliran kesaksian dari salah seorang kerabat yang juga turut dalam penerbangan tersebut, namun luput dari maut. Kesaksiannya memberikan insight bagi penulis, dan dalam kesempatan ini ingin penulis bagikan kepada para pembaca.
Indra (bukan nama sesungguhnya) terbang bersama ipar perempuannya ke Jogjakarta, di dalam pesawat Garuda yang naas tersebut. Ia menceritakan bahwa saat menjadi jelas bagi para penumpang bahwa pesawat sedang meluncur tak terkendali, kepanikan melanda. Kebanyakan penumpang menjerit, dan sebagian lagi berseru kepada Tuhan menurut cara agamanya masing-masing. Suatu fenomena yang unik dialami Indra. Saat detik-detik kritis itu berlangsung – dan segala sesuatu berlangsung dengan begitu cepat – Indra merasakan segala sesuatu berjalan dalam slow motion. Ia sendiri sangat heran bahwa dalam situasi paling genting tersebut ia dapat menyaksikan segala sesuatunya dengan sangat jelas. Aneh tapi nyata, bila pada kebanyakan orang dalam situasi tersebut, kesadaran akan menyusut bahkan sampai hilang (pingsan); Indra merasakan suatu konsentrasi kesadaran yang belum pernah dialaminya, sehingga segala sesuatu menjadi sangat jelas disaksikannya.
Setelah pesawat meledak dan mulai terbakar, orang-orang berlomba-lomba menyelamatkan diri. Saat itu Indra dihadapkan pada pilihan tersulit dalam hidupnya. Ia duduk dekat pintu keluar sehingga dapat dengan segera menyelamatkan diri; tetapi iparnya duduk jauh di depan, di mana api dan asap telah menutupi pandangan. Indra harus memilih, apakah ia akan menyelamatkan diri segera – atau mencoba menyelamatkan iparnya yang kemungkinan besar terjebak di barisan depan. Tidak ada banyak waktu untuk berpikir, tidak ada orang lain untuk diminta pendapatnya, bahkan Indra merasakan bahwa Tuhan diam dan tidak memberikan petunjuk pilihan mana yang harus diambilnya. Pilihan harus dibuatnya segera, sendiri. Indra memilih untuk keluar, menyelamatkan diri. Sambil melakukannya, hatinya dihunjam rasa bersalah dan cela diri. Suara hatinya terdengar jelas,”Aku seorang pengecut!! Seharusnya aku menyelamatkan iparku yang mungkin terpanggang api di sana..”
Dinamika intrapsikis yang dialami Indra seolah membenarkan pendapat Sigmund Freud tentang hakikat manusia. Ia mengatakan bahwa manusia pada dasarnya bersifat narcissistic. Di lubuk hatinya yang paling dalam, manusia hanya mementingkan dirinya sendiri dan menomorsatukan keselamatannya sendiri. Saat tekanan menjadi terlalu besar, Ego hancur dan suara Superego diabaikan. Yang meraja adalah Insting dasar yang irasional: Self-preservation, yaitu bagian dari Insting hidup yang bersifat biologis, untuk survive. Maka tidak heran kalau Freud bersikap pessimistic tentang kemanusiaan.
Indra berjalan dengan penuh sesal diri di pesawahan di mana sebagian korban yang selamat terbaring luka-luka. Di sana ia melihat…iparnya terbaring dengan hanya luka-luka ringan. Suatu petir menyambar benak Indra. Ia baru saja merasa gagal menghadapi “ujian” moral dan iman ketika menghadapi pilihan antara hidup dan mati tersebut. Ia telah melakukan pilihan yang keliru secara moral, yaitu memilih untuk bersikap pengecut, menyelamatkan dirinya sendiri, tidak menolong iparnya. Absurdnya adalah: rupanya pilihannya tepat. Karena kalau ia mengikuti dorongan rasa bersalahnya untuk memaksakan diri menyelamatkan iparnya, maka kemungkinan besar ia akan turut terpanggang di dalam pesawat, sementara iparnya sesungguhnya sudah selamat di luar. Mana yang benar? Mana yang salah? Pilihannya yang salah secara moral, telah membawanya pada jalan hidup.
Para pembaca yang budiman, mohon jangan salah tangkap. Pesan dalam cerita yang ingin penulis bagikan melalui cerita di atas tentunya bukan suatu seruan untuk mengesampingkan pertimbangan moral dan mengambil sikap SDM (Selamatkan Diri Masing-masing). Tetapi, seperti Indra yang bersaksi dengan penuh ketakjuban akan misteri Ilahi, penulis pun hendak mengajak para pembaca masuk dalam misteri hidup ini.
Dalam menjalani keberadaan kita yang rapuh di dunia ini, berkali-kali kita dihadapkan pada persimpangan jalan. Seperti Indra, kita pun seringkali harus segera membuat keputusan seorang diri, tanpa cukup informasi untuk mengambil keputusan yang bijaksana. Tiada orang untuk bertanya, dan Tuhan pun “diam”. Dan seperti Indra, kita pun berkali-kali sudah membuat keputusan-keputusan yang keliru. Barangkali kitapun malu pada diri sendiri karena terbukti tidak punya cukup nyali dan tidak dapat mengambil keputusan yang heroic dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang sering kita khotbahkan. Tapi inilah misterinya: Tuhan rupanya tidak selalu menggunakan kekuatan, keberanian dan kebenaran dalam diri seorang manusia untuk mencapai maksudNya. Tuhan pun kadang menggunakan kelemahan dan kesalahan manusia.
Kira-kira dua ribu tahun yang lalu, seorang murid Yesus yang dipandangNya paling kuat karakternya, sehingga diberi nama julukan “batu karang”, juga melakukan kesalahan yang sama. Petrus yang berkoar akan mati bersama-sama Yesus, ternyata hancur nyalinya di detik-detik yang paling menentukan. Ia menyangkal Yesus sampai tiga kali, untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dan ketika ia memandang wajah Yesus setelah penyangkalannya yang ketiga, ia menangis dengan sedihnya karena ia sadar betapa pengecutnya dirinya. Tetapi misterinya adalah: Tuhan membentuk karakter Petrus bukan dengan menunjukkan ketegaran dan keheroikan dirinya, tapi justru dengan membawa Petrus ke titik nadir konsep dirinya. Petrus dihadapkan pada wajah karakternya yang sesungguhnya; dan wajah itu buruk rupa: Petrus adalah seorang pengecut. Gambaran dirinya yang ideal hancur. Namun, dari puing-puing konsep diri inilah Yesus membentuk seorang Rasul yang gagah berani dan kelak menjadi martirnya dengan disalib terbalik, menjadi fondasi Gereja. Saya berpikir, seandainya Petrus bersikap gagah perkasa saat Yesus ditangkap, barangkali Yesus akan senang karena Petrus sudah bersikap baik dan benar; namun Yesus pun akan kehilangan salah seorang saksiNya yang paling berharga kelak.
Buat saya, insight di atas menjadi suatu kabar baik yang membebaskan. Yesus memang memerintahkan kita untuk menjadi sempurna, sama seperti Bapa di Sorga juga sempurna. Tetapi, Yesus pun mengenal hati manusia, karena Ia yang menciptakan kita. Konsep Yesus tentang kesempurnaan, rupanya masih memberi ruang untuk kesalahan dan kemanusiawian. Ketika Yesus bertemu lagi dengan Petrus sesudah kebangkitanNya, Ia tidak bertanya,”Simon, anak Yohanes, apakah engkau sudah menjadi berani dan sempurna sekarang?” Ia bertanya,”Simon, anak Yohanes, apakah engkau mencintai Aku?” Dan Ia mendirikan GerejaNya bukan dengan sekumpulan hero yang adimanusiawi, melainkan dari sekumpulan manusia yang sekalipun kadang lemah, namun sungguh-sungguh mencintaiNya.
Cintalah yang pada akhirnya menjadi ukuran. Melalui mata cinta, kita dapat memandang melampaui batasan ketidaksempurnaan diri dan sesama, melampaui absurditas dan keirasionalan hidup ini. Di dalam Cinta, selalu ada harapan. Cinta mengatasi segala-galanya dan hanya di dalam Cinta-lah Kerajaan Allah dapat didirikan.
Iman Setiadi Arif
Staf pengajar Fakultas Psikologi Ukrida – Jakarta
Kamis, 28 Juni 2007
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
.jpg)
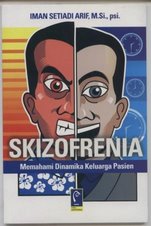
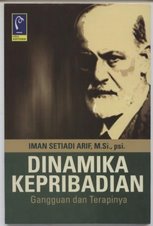



Tidak ada komentar:
Posting Komentar