Melampaui Batasan Keberadaan
Tulisan ini pernah dimuat di Harian Suara Pembaruan
Miyamoto Musashi adalah seorang legenda Samurai yang hidup di era Tokugawa (antara tahun 1603 – 1867) di Jepang. Pada masanya, ia adalah pendekar yang tak terkalahkan. Ia berkeliling negeri, menantang dan mengalahkan perguruan-perguruan Samurai paling ternama, seperti Yoshioka dan Yagyu dan terakhir ia mengalahkan Sasaki Kojiro - seorang pendekar terhebat (dan terganas) di masa itu - dengan hanya menggunakan pedang kayu yang dirautnya sebelum pertempuran dimulai. Setelah itu ia tidak pernah bertempur lagi, sekalipun banyak pendekar muda bermunculan dengan ambisi untuk mengalahkannya. Di masa tuanya ia lebih terkenal sebagai ahli kaligrafi, tembikar, upacara minum teh dan pelukis. Ia menulis buku yang berjudul “Buku tentang lima cincin”, yang sekarang banyak menjadi sumber inspirasi bagi para manager dalam mengelola bisnis di tengah persaingan yang ketat.
Musashi berasal dari keluarga Samurai miskin. Ayahnya otoriter dan keras luar biasa, sehingga ibu Musashi tidak tahan dan meninggalkannya beserta kedua anaknya yang masih kecil. Musashi tumbuh menjadi pemuda berandalan, sampah masyarakat yang ditakuti dan dibenci warga kampungnya. Sampai suatu ketika ia bertemu dengan seorang guru Zen bernama Takuan Soho yang membangkitkan pencerahan dalam dirinya. Dalam pencerahan itu ia menyadari bahwa hidup adalah batu permata yang masih harus digosok dari waktu ke waktu hingga sinar cemerlangnya muncul. Seorang Samurai menimang-nimang permata tersebut dengan penuh kasih sayang sampai tiba saatnya untuk menyerahkannya dengan penuh kehormatan dalam menjalankan kewajiban. Sejak perjumpaan dengan Takuan, dimulailah petualangannya mencari kesejatian melalui jalan pedang.
Setelah mengalahkan lawan-lawan paling berat dan berulangkali selamat setelah berhadapan muka dengan muka dengan maut, Musashi tidak merasakan kepuasan sejati. Tidak ada lagi yang bisa diraih dan ia merasa menghadapi jalan buntu. Dalam keputusasaannya ia (kembali) berjumpa dengan seorang guru Zen yang bernama Gudo, yang membuka mata hatinya sehingga ia mencapai pencerahan kedua yang membawanya pada kesempurnaan. Pendakian kesempurnaan yang dilalui Musashi dapat digambarkan melalui tiga tahap. Di tahap pertama pedang dan pendekar menyatu sehingga dengan menggunakan ranting, bambu atau bahkan selembar daun saja si pendekar dapat membunuh lawannya. Di tahap kedua: pedang tidak lagi memiliki wujud, melainkan ada di hati si pendekar, sehingga dari jarak 100 mil pun ia dapat membunuh lawannya. Di tahap tertinggi, tidak ada pedang – tidak ada pendekar, tidak ada lagi keinginan untuk membunuh, sang Pendekar (dengan “P”) merangkul segalanya dan hanya kedamaian yang tersisa.
Perjuangan Ego mencapai Superioritas
Cerita di atas adalah metaphor yang baik sekali untuk menggambarkan perkembangan kepribadian manusia. Seorang psikoanalis bernama Alfred Adler (1930) berteori tentang perjuangan Ego untuk melakukan kompensasi atas inferioritasnya menuju keadaan Superior. Dalam proses kompensasi itu seseorang mula-mula menjadi agresif, kemudian beralih menjadi ingin menguasai orang-orang lain dan kemudian berjuang mencapai keadaan unggul (state of excellence/superior). Seperti Musashi yang dari hari ke hari menempa keterampilannya berpedang, manusia terus meningkatkan kekuatan Ego nya dalam pergumulan hidup sehari-hari.
Kepribadian yang sehat membutuhkan Ego yang kuat. Ego yang kuat merupakan suatu pencapaian yang luar biasa, sebagai hasil pergumulan dalam kehidupan. Erik H. Erikson (1950, 1968) dengan teori perkembangan psikososialnya telah menerangkan bagaimana Ego berkembang mencapai kematangan, setelah melewati berbagai krisis sejak masa kanak-kanak sampai di usia lanjut.
Ego yang kuat ditandai oleh kesediaan untuk menunda kesenangan dan suatu kegairahan untuk meningkatkan efektivitasnya terus menerus dalam berinteraksi dengan lingkungan. Seperti Musashi muda yang haus kemenangan, Ego yang kuat selalu beralih dari satu prestasi ke prestasi lain, mencari tantangan baru yang lebih sulit untuk ditaklukkan.
Puncak pencapaian Ego adalah yang disebut oleh Abraham Maslow sebagai aktualisasi diri. Dalam kondisi aktualisasi diri, seseorang telah memaksimalkan realisasi potensi-potensi dirinya. Segenap bakat dan kemungkinannya untuk berprestasi telah diwujudkan sehingga seseorang telah mencapai kondisi Superior. Apakah hal ini menimbulkan kepuasan yang sejati? Seperti contoh dalam cerita Musashi di atas, jawabannya adalah tidak. Kondisi di mana seseorang berada di puncak superioritas, seringkali menimbulkan konflik yang lebih besar dan membuatnya terisolasi dari orang-orang lain. Dari penjara Inferioritas, ia masuk ke penjara Superioritas.
Transendensi untuk melampaui keterbatasan Ego
Untuk mencapai pembebasan sejati, Ego yang sempit harus dilampaui. Ken Wilber (1996) mengatakan dengan ringkas dan padat: Perkembangan adalah Evolusi; Evolusi adalah Transendensi; dan Transendensi menuju pada tujuan akhir yaitu Atman, atau kebersatuan kesadaran di dalam Tuhan. Di dalam kondisi Atman inilah seseorang dapat melampaui kekerdilan dan kedangkalannya menuju keluasan dan kedalaman. Dalam kondisi inilah damai diperoleh.
Sebelum seseorang mencapai realisasi diri final berupa Atman, kepribadian berada di bawah rezim Ego. Keberadaan di bawah rezim Ego adalah keberadaan yang dangkal, sempit dan penuh keterpecahan. Erich Fromm (1947, 1955, 1964) melukiskan kondisi dasar manusia yang penuh kontradiksi di bawah rezim Ego. Manusia memiliki ciri-ciri kebinatangan, tapi ia bukan binatang. Manusia merupakan bagian dari alam, tapi ia juga terpisah dari alam. Manusia rindu untuk mengalami kebersamaan dan persaudaraan sejati dengan orang lain, tapi ia tak hentinya membenci dan menghancurkan sesamanya. Bahkan di dalam dirinya sendiripun manusia penuh keterpecahan. Bagian dirinya yang satu membenci dan menolak bagian dirinya yang lain, dan manusia selalu menemukan dirinya melakukan sesuatu yang tidak dikehendakinya atau tidak melakukan apa yang sesungguhnya dikehendakinya, sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus. Keterpecahan ini menimbulkan keterasingan dan kesepian mendalam yang menurut Erich Fromm merupakan akar segala perilaku menyimpang dan destruktif manusia.
Puasa dan Matiraga untuk “Mematikan” Ego, membangkitkan Atman
Untuk melampaui keterbatasan Ego, seseorang mesti “mematikan” Ego. Mungkin kita boleh mengutip kata-kata Yesus yang mengatakan bahwa jika biji tidak mati, maka ia tetap tinggal biji; namun jika ia musnah, maka berbuah berlimpah-limpah.
Di dalam setiap agama dan aliran kepercayaan, terdapat berbagai ritus matiraga yang sakral untuk “mematikan” Ego dan mencapai keadaan Moksha (Pembebasan/Pencerahan). Salah satu ritus universal adalah dengan berpuasa. Saat seseorang berpuasa – agama apapun yang dianutnya – ia “mematikan” kedagingannya untuk memperoleh kebangkitan rohani.
Beth Hedva (2001), seorang psikolog transpersonal, mengatakan bahwa proses “mematikan” Ego tidak satu kali jalan, melainkan dilakukan berulangkali melalui siklus kematian simbolik-kelahiran kembali. Jalan universal yang harus ditempuh seseorang menuju pembebasan adalah melalui lima tahap yang harus dilalui berulang kali.
Tahap pertama: Perpisahan (Separation) dari segala hal yang mengikat kita pada keduniawian dan kedagingan kita. Tahap kedua: Pemurnian (Purification) dari segala kemelekatan yang menimbulkan konflik dan penderitaan. Tahap ketiga: Kematian simbolik (Symbolic death) di mana cangkang Ego kita yang sempit dihancurkan. Tahap Keempat: Pencerahan (New Knowledge), di mana kita memperoleh perspektif baru dalam memandang diri, dunia dan orang lain. Kelima: Kelahiran kembali (Rebirth) di mana seluruh diri diperbaharui, dari kekerdilan menjadi keluasan, dari kedangkalan menjadi kedalaman, dari konflik menjadi damai. Dan selanjutnya siklus ini dimulai kembali sampai kita mencapai tujuan final berupa Atman.
Miyamoto Musashi telah menempuh jalan jalan pedang untuk mencari kesejatian diri dan pembebasan. Di akhir perjalanannya, pedang lenyap dan diri (Ego) juga lenyap. Kita pun mesti menempuh jalan kita masing-masing, yang sekalipun kelihatannya berbeda-beda, namun sebenarnya universal, yaitu jalan menuju Pembebasan. Bulan Ramadhan yang baik ini tidak hanya anugerah bagi kaum Muslim, melainkan mengingatkan semua orang yang rindu pada Pembebasan, untuk menempuh jalannya, matiraga dan melampaui kungkungan keberadaannya. Selamat Berpuasa…
Iman Setiadi Arif
Dekan dan staff pengajar Fakultas Psikologi Universitas Kristen Krida Wacana – Jakarta
Kamis, 28 Juni 2007
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
.jpg)
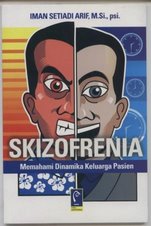
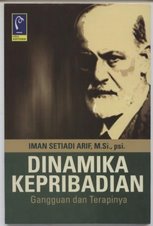



Tidak ada komentar:
Posting Komentar