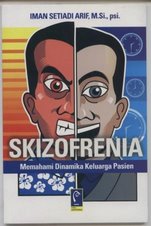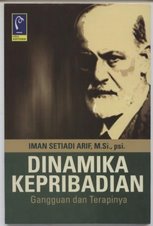Unedited version. Edited version appear on Intisari Nov 2008
Krisis finansial global yang bermula dari daratan Amerika sudah memakan banyak korban; bukan cuma kerugian investasi yang secara global nilainya sudah trilyunan dollar, melainkan juga bertambahnya orang-orang yang mengalami stres, depresi dan bahkan melakukan bunuh diri. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Amerika, melainkan korban mulai berjatuhan pula di daratan Asia, termasuk di Indonesia.
Semua orang gempar saat Rony (bukan nama sesungguhnya) terkena stroke. Ia adalah seorang wiraswastawan muda yang sukses dan tokoh masyarakat yang terkemuka. Saat ia baru menginjak usia 35 tahun, ia sudah berhenti dari posisinya sebagai top manager di suatu perusahaan mutlinasional, dan mendirikan perusahaannya sendiri. Perusahaannya pun segera meroket, dan Rony segera menikmati hidup impian ala Kiyosaki yang bagi kebanyakan orang hanyalah janji surga: Kebebasan (baca: keberlimpahan) Finansial; plus dikagumi kawan, disegani lawan (competitor) dan dipuja serta menjadi sumber iri hati semua orang. “Karir” sosialnya pun segera menanjak, di mana ia menduduki posisi puncak di organisasi kemasyarakatan tempatnya bergiat, yang biasanya jarang sekali diduduki oleh orang yang belum putih semua rambutnya.
Dalam kehidupan pribadinya, Rony menjalani diet yang sehat dan seorang yang rajin – bahkan sangat kompetitif – dalam sport yang digelutinya. Ia pun jauh dari gossip dan menjalani hidup tanpa cela bersama keluarganya. Pendeknya, hidup Rony adalah contoh gemilang seorang “pemenang” sejati yang meraih semua ambisinya, karena disiplin dan kerja kerasnya sendiri, jauh meninggalkan semua teman-teman sebayanya. Sampai akhirnya…krisis finansial global menghantamnya tanpa sempat diantisipasinya. It’s a wake up call.
Citius, Altius, Fortius?
Kehidupan Rony sepintas tampak sebagai contoh sempurna penerapan semboyan Olympiade: Lebih cepat, lebih tinggi, lebih kuat (Citius, Altius, Fortius). Kehidupannya dibingkai seperti gelanggang pertandingan, di mana ia selalu memacu diri memecahkan record yang ada, di mana pemegang record sebelumnya adalah dirinya sendiri. Rony adalah perwujudan ideal etos kerja yang sering didengung-dengungkan para motivator yang menjual pemeo-pemeo tentang kesuksesan. Rony tidak pernah puas pada segala sesuatu yang sudah diraihnya, dan ia benci akan sesuatu yang biasa-biasa saja. Ia hanya dapat menerima excellence standard dalam apapun yang dikerjakannya. Ia tidak pernah terlena di zona kenyamanan dan selalu mencari tantangan baru. Ia bersikap keras pada semua orang yang bekerja kepadanya, namun semua orang pun tahu bahwa ia lebih bengis lagi pada dirinya sendiri. Menunggu, pasrah dan bersabar, tidak ada dalam kamus hidupnya; dan semua orang memujanya dan ingin menjadi seperti dirinya, justru karena sifat-sifat “positif” nya tersebut. Lalu kenapa orang “sebaik” itu terkena stroke?
Gading yang rapuh
Kebanyakan orang yang sudah terkena cuci otak oleh pengarang buku-buku laris tentang kesuksesan, akan mengamini gaya hidup seperti yang dijalani oleh Rony. Orang seperti Rony adalah pahlawan mereka. Namun, bila gambaran sempurna ini ditelaah lebih teliti, orang akan melihat hal-hal “kecil” yang sepintas akan terlewatkan: Rony bukanlah pendengar yang baik, ia seringkali bicara dengan cepat dan meledak-ledak; ia sangat tidak sabar akan kelambatan dan berbagai antrian, serta ingin melakukan berbagai kegiatan sekaligus; ia akan sangat gelisah bila tidak sedang sibuk, dan ia berpusat pada dirinya sendiri, tidak hirau pada perasaan orang lain selain menampilkan empati yang artificial. Orang-orang pun tidak tahu, kecuali istrinya, bahwa Rony seringkali tidak bisa tidur sehingga ia semakin sering minum obat tidur saat masuk peraduan, dan kemudian harus memaksa diri bangun di pagi buta saat kantuk masih menggelayuti pelupuk mata. Tanpa disadarinya tekanan darahnya tinggi dan tingkat cholesterol-nya mulai melewati ambang toleransi. Kenyataannya adalah: dirinya sendirilah yang memacu tubuh dan jiwanya di luar batas sehingga stroke hadir dalam hidupnya. Krisis finansial yang dialami sekarang, hanyalah jalan untuk menggenapi konsekuensi dari pilihan hidupnya.
Meyer Friedman, seorang dokter ahli jantung ternama, membuat suatu istilah yang populer untuk pola perilaku sebagaimana ditunjukkan oleh Rony: Kepribadian tipe A, yaitu kepribadian yang terlalu ambisius dan selalu gelisah serta tak puas pada segala yang ada. Menurut teori mereka, dasar dari pola perilaku ini adalah self-esteem yang rendah dan rasa tidak aman yang akut, yang mungkin sekali tidak disadari oleh yang bersangkutan. Kontras dari kepribadian tipe A adalah kepribadian tipe B yang biasanya digambarkan sebagai pribadi yang sabar, rileks, lebih nrimo dan nyantai (sifat-sifat yang konotasinya adalah ndeso dan tidak disukai oleh masyarakat kota yang hyper-competitive). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Friedman & Rosenman selama 9 tahun pada lebih dari 3000 pria sehat berusia 35-59 tahun, kepribadian tipe A terkait erat dengan sakit jantung koroner dan berbagai penyakit lain yang disebabkan oleh stres. Sekalipun ada studi lebih baru yang tidak mendukung penelitian Friedman dan Rosenman, tetapi bukan berarti penelitian mereka salah, karena stres dan gaya hidup yang serba cepat memang terkait erat dengan berbagai penyakit kronis, seperti sakit jantung koroner, darah tinggi, insomnia, dll – sekalipun mungkin korelasinya tidak selangsung dan sesederhana sebagaimana digambarkan oleh Friedman dan Rosenman.
Tetapi apapun juga, kalau kita bertanya pada kebanyakan orang-orang cosmopolitan seperti Jakarta, kepribadian manakah yang dianggap lebih baik, maka jawabannya akan jelas: kepribadian yang serupa dengan tipe A. Siapa kiranya yang tidak ingin menjadi orang yang tampaknya merupakan gambaran orang yang sukses dan disukai semua orang; ambisius, kompetitif, dan pemenang. Dan sebaliknya, siapa kiranya yang di hari-hari ini mau menjadi si Kabayan, yang santai, sabar dan nrimo?
Sabar? Hari gini? Are you nuts?
Kesabaran, sikap menerima (nrimo), kepasrahan, hidup yang rileks, adalah beberapa sifat yang hari-hari ini dijauhi orang bagaikan penyakit sampar. Sifat-sifat itu dianggap tidak adaptif – atau bahkan kontra produktif – bagi kepentingan survival of the fittest, sebagaimana dituntut oleh kehidupan di kota besar. Apakah anda dapat menyetir mobil dengan sabar di Jakarta – di tengah kepungan motor-motor yang berseliweran dengan ganasnya? Ha..ha..ha.. anda pasti sedang bermimpi. Apakah anda mau bersikap nrimo di tengah sikut-sikutan dan saling menjatuhkan dalam politik kotor di kantor anda? Selamat..Anda akan segera masuk surga..dalam arti sesungguhnya, yaitu mati konyol. Apakah anda mau bersikap pasrah pada perlakuan boss anda di kantor? Salut..anda baru saja mendaftarkan diri menjadi keset yang akan diinjak-injak kapan saja dibutuhkan.
Point-nya jelas: di dunia modern ini, di kota-kota besar seperti di Jakarta, kesabaran dan berbagai sifat mulia (virtue) lainnya, hanya akan dianggap sebagai suatu kebodohan dan sikap naïf yang kekanak-kanakan; warisan pendidikan feodal khas inlander, yang harus segera “dicerahkan” oleh cahaya pendidikan (Barat) yang modern. Bahkan mungkin sifat-sifat ini dianggap membahayakan sehingga harus segera dikikis, karena akan membuat anda digilas oleh deru kehidupan kota yang beringas. Paling banter sifat-sifat itu hanya dianggap suatu ideal yang dimuliakan di bibir, namun segera menguap saat menghadapi kenyataan hidup yang keras. Saya yakin, kebanyakan dari kita masih memberikan nasihat-nasihat pada anak kita untuk menjadi sabar, pengasih, menerima, dll dengan bibir kita; namun dengan perilaku kita, sesungguhnya kita mengajar mereka untuk jadi cerdik, licik, gesit, nyerobot, dan nyikut. Barangkali dalam hati kecil kita menganggap sifat-sifat mulia itu hanya dapat terlaksana di Surga mulia, nanti.. bukan sekarang di dunia ini.
Kesabaran vs. Ketergesaan
Namun justru kenyataan hidup yang penuh stres dan segala konsekuensinya yang merugikan pada kesehatan tubuh, kewarasan jiwa dan kejernihan spiritual, yang menyadarkan kembali orang-orang pada kebijaksanaan kuno itu. Sabar – bukanlah sifat yang maladaptif, sebaliknya mungkin merupakan salah satu benteng terkuat yang mungkin dimiliki seseorang menghadapi gerusan stres setiap harinya. Kehausan akan revitalisasi tubuh, jiwa dan roh mendorong manusia modern untuk menggali kembali sumber-sumber kebijaksanaan kuno yang lama terlupakan.
Salah seorang tokoh yang mengadaptasi dan mengarusutamakan kembali kebijaksanaan Timur yang terlupakan ini adalah Jon Kabat-Zinn. Dia adalah seorang psikolog dan Professor of Medicine Emeritus di University of Massachusetts Medical School. Sejak tahun 1979 ia mendirikan Stress Reduction Clinic untuk mengantisipasi fenomena stres yang makin marak di saat itu. Antisipasinya sangat tepat karena dewasa ini, stres sudah menjadi salah satu gangguan utama manusia modern. Jon mendasarkan metodenya pada spiritualitas dan falsafah Tibetan Buddhism dan berbagai spiritualitas Timur lain. Ia menyebut tekniknya sebagai Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR).
Falsafah dasar teknik ini adalah mengenal perbedaan antara “Doing” dan “Being”. “Doing” adalah suatu modus keberadaan di mana seseorang mengarahkan dirinya keluar untuk melakukan dan mencapai sesuatu. Dalam modus “Doing” seseorang memusatkan perhatiannya ke luar dirinya, yaitu pada objek yang dikehendakinya, dan mengerahkan segala daya upaya untuk meraih objek tersebut. Di dalam modus “Doing” seseorang berpikir bahwa dirinya tidak utuh dan tidak sejahtera bilamana tidak memiliki objek yang dikehendakinya; dan sebaliknya ia terjebak pada pandangan keliru bahwa ia hanya akan menjadi bahagia dan utuh kalau berhasil meraih objek tersebut; dan ia akan merana dan menderita bila gagal memperoleh objek tersebut. Fokus dan penempaan diri terus menerus pada “Doing” akan menjadikan orang pada akhirnya memiliki pola perilaku seperti kepribadian tipe A, yang rentan pada stres, selalu tergesa-gesa dan tidak puas pada apapun yang ada. Tokoh kita Rony adalah contoh sempurna orang yang terjebak pada “Doing”.
“Being” atau disebut juga “Non-Doing” (dalam istilah Taoism: “Wu Wei”) adalah modus keberadaan lain yang mengatakan bahwa hal-hal yang paling penting dalam hidup ini bukan dicapai dengan berusaha – apalagi berusaha keras – melainkan justru dengan tidak berusaha, atau dengan kata lain dengan membiarkannya terjadi secara alami. Seseorang yang berada dalam modus keberadaan “Being” ini, tidak menghendaki apapun juga, melainkan membiarkan segala sesuatu terjadi dan mengalir bersama semesta. Tentunya ini bukan berarti seseorang yang berada dalam modus “Being” tidak bekerja dan bermalas-malasan, menunggu segala sesuatu terjadi baginya. Ia tetap bekerja, namun dengan sikap batin yang berbeda dan dengan pengosongan diri. Justru karena ia mengosongkan dirinya, sepi ing pamrih, tidak menentang apapun juga, dan taat sepenuhnya pada hukum alam maka semesta alam mendukungnya dengan kekuatan tak terhingga. Ia sabar akan segala sesuatu dan menerima segala sesuatu, sehingga segala sesuatu tunduk padanya. Di balik sikap sabar dan menerima ini, terdapat kesadaran penuh akan identitas diri yang sejatinya sudah baik; bahwa sesungguhnya ia tidak perlu pergi ke manapun, tidak perlu berupaya menjadi siapa pun, dan tidak perlu meraih apapun untuk menjadi utuh. Sejatinya ia sudah lengkap, utuh dan kebahagiaan sudah selalu ada dalam dirinya sendiri untuk ditemukan dan dibiarkan mekar, bukan diciptakan dan diusahakan dengan kekerasan. Dengan sendirinya muncul sikap sabar yang sekalipun lembut namun tak dapat dikalahkan oleh kekerasan apapun. Kesabaran, seperti juga iman, dapat memindahkan gunung. Leo Tolstoy mengatakan bahwa “The most powerful warriors are patience and time.”
Apa yang harus dilakukan untuk menjadi sabar?
Dengan semakin terbukanya kesadaran orang-orang tentang perlunya mengembangkan kesabaran, sikap menerima dan kelenturan dalam menghadapi kerasnya kehidupan maka marak pula gerakan untuk menggali kembali kebijaksanaan dan sifat-sifat mulia yang lama terlupakan. Ruang tulisan yang ada ini tentunya memang tidak ditujukan untuk dapat memberikan petunjuk yang lengkap tentang jalan dan proses yang harus dijalani untuk mencapainya. Saya harapkan ini hanya menjadi undangan bagi anda untuk melanjutkan mencari petunjuk-petunjuk yang lebih lengkap dan paling cocok untuk diri anda. Ada bermacam-macam teknik dan aliran yang dapat anda pilih, tetapi prinsipnya kesemuanya menekankan pada realisasi diri dalam tiga hal: Latihan Tubuh, Restrukturisasi Pikiran dan Pengembangan Spiritualitas.
Latihan-latihan tubuh
Tubuh merupakan bagian penting dari diri yang tak dapat dikesampingkan bila anda bermaksud untuk merealisasikan diri dan mengembangkan kesabaran. Bila tubuh anda gelisah dan penuh dengan ketegangan maka upaya untuk menjadi sabar akan menjadi mustahil. Berbagai kebiasaan buruk dan stres yang dialami bertahun-tahun telah terekam dalam tubuh sehingga tubuh menjadi sangat reaktif dan tegang. Untuk menghapus pembelajaran yang keliru itu, berarti harus mendidik ulang respon tubuh anda. Daniel Goleman, pengarang buku laris Emotional Intelligence dan Social Intelligence telah menjelaskan dalam buku-bukunya bahwa berbagai emosi dan kecerdasan yang diperlukan untuk dapat mengelolanya, berakar pada tubuh. Melatih kesabaran – yang merupakan salah satu perwujudan kecerdasan emosional – berarti pula melatih tubuh. Anda tidak dapat menjadi sabar hanya dengan menanamkan dogma-dogma tentang kesabaran. Tubuh anda mesti menjadi sabar dan rileks; agar emosi dan kecerdasan anda dapat turut menjadi jernih pula. Latihan-latihan tubuh seperti relaksasi, meditasi, yoga, tai-chi, dll dapat membantu anda mendidik kembali tubuh anda.
Restrukturisasi pikiran
Psikologi Barat yang diwakili oleh tokoh-tokoh aliran Cognitive, dan Psikologi/Spiritualitas Timur seperti Zen Buddhism telah lama menyadari pentingnya pikiran sebagai nakhoda yang menggerakkan emosi dan tindakan. Sebelum ada tindakan yang nyata berupa tingkah laku, sudah ada gerakan internal berupa dialog dalam diri (Self talk), yang sekalipun mungkin tidak disadari, sangat besar pengaruhnya pada apa yang akan anda rasakan dan akan anda lakukan. Upaya menjadi sabar, berarti proses mengenali dan mengelola dialog dalam diri ini. Dialog internal yang sifatnya negatif dan irasional akan mendorong anda menjadi gelisah, takut dan karenanya melakukan tindakan-tindakan yang akan anda sesali kemudian; sebaliknya dialog internal yang positif dan rasional akan menghasilkan perasaan yang tentram dan tindakan yang adaptif. Sabar atau tidaknya seseorang seringkali ditentukan oleh dialog apa yang berlangsung dalam dirinya. Biasanya, dibutuhkan bimbingan seorang terapis atau guru spiritual untuk membantu anda mengenali dan mengubah dialog internal dalam diri ini.
Pengembangan Spiritualitas
Latihan-latihan tubuh dan restrukturisasi pikiran pada akhirnya bermuara pada pengembangan spiritualitas. Spiritualitas adalah fondasi utama untuk membangun kesabaran dalam diri. Bila seseorang berakar dalam spiritualitas (baca: tidak selalu identik dengan ritual agama), maka hidupnya seolah dipancangkan pada fondasi yang sangat kuat, sehingga secara alami kesabarannya berkembang. Ia tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai peristiwa dalam hidup yang tidak kekal. Kata-kata dari St. Theresia Avilla berikut ini dengan tepat sekali menyampaikan bagaimana seseorang yang bertumbuh dalam spiritualitas akan menjadi sabar dan karenanya dapat menghadapi perubahan apapun dalam hidupnya. “Let nothing disturb you, let nothing make you afraid. All things are passing. God alone never changes. Patience gains all things. If you have God you will want for nothing. God alone suffices.” Semoga kita semua dapat menemukan kembali mutiara yang terlupakan dalam diri kita, yaitu kesabaran; yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
Jakarta, 30 October 2008
Dekan Fakultas Psikologi Universitas Kristen Krida Wacana (UKRIDA).
Iman Setiadi Arif, M.Si., Psi


.jpg)